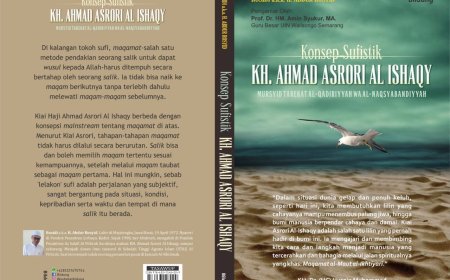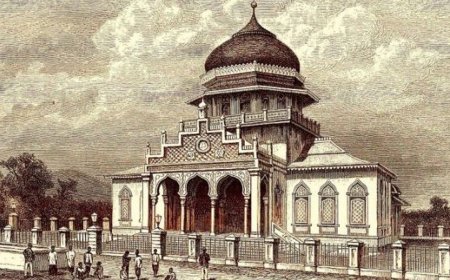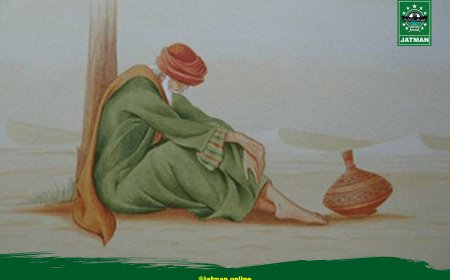Mewaspadai Arus Bawah Perpecahan: Menjemput Gelombang Ketiga NU
Tahun-tahun antara 2025 hingga 2030 tidak hanya akan menjadi babak sejarah politik Indonesia yang krusial, tetapi juga medan kontestasi ideologis yang menentukan arah masa depan umat Islam Nusantara

Tahun-tahun antara 2025 hingga 2030 tidak hanya akan menjadi babak sejarah politik Indonesia yang krusial, tetapi juga medan kontestasi ideologis yang menentukan arah masa depan umat Islam Nusantara. Sebuah narasi keras, yang mengklaim adanya upaya sistematis dari jaringan Wahabi dan simpatisan asing untuk membubarkan Nahdlatul Ulama (NU), mungkin terdengar berlebihan bagi sebagian pihak. Namun di balik retorikanya yang berapi-api, terdapat panggilan mendesak yang tak bisa diabaikan: NU sedang menghadapi tantangan eksistensial yang perlu dijawab dengan kepala dingin dan strategi jangka panjang.
Kita menyebut masa ini sebagai Gelombang Ketiga NU. Gelombang pertama adalah kelahiran NU pada 1926, di tengah badai kolonialisme dan modernisme. Gelombang kedua lahir pada masa Orde Baru hingga awal Reformasi, saat NU memainkan peran penting dalam stabilitas nasional, pendidikan pesantren, dan perumusan format Islam moderat Indonesia. Maka kini, Gelombang Ketiga NU bukan sekadar kebangkitan struktural, tapi kebangkitan spiritual, intelektual, dan digital.
Target Perpecahan: Antara Fakta dan Fiksi
Kekhawatiran tentang proyek besar "menghapus NU dari peta Indonesia" bukan tanpa dasar. Ada gelombang konservatisme transnasional yang menyusup melalui pendidikan, media sosial, hingga dakwah daring, yang membawa misi pemurnian Islam versi Timur Tengah dan memosisikan tradisi Islam Nusantara sebagai bid'ah atau bahkan syirik. NU, dengan tradisi tahlilan, manaqiban, maulidan, ziarah kubur, dan penghormatan kepada Ahlul Bait, menjadi target alami paham Wahabi dan turunannya.
Namun bahaya lebih besar datang bukan dari luar, tetapi dari dalam, saat warga NU sendiri tak menyadari medan perang baru: perang narasi, perang simbol, perang algoritma. Ada kader-kader NU yang tercerabut dari akar epistemologi pesantren, lalu menjadi corong ideologi asing, menjelma menjadi buzzer yang menyerang ulama sendiri. Inilah era ketika kiai disamakan dengan penjual agama, dan hoaks menjadi lebih dipercaya daripada fatwa.
Literasi Tiga Warna: Kuning, Putih, Abu-Abu
Dalam menyongsong Gelombang Ketiga, NU perlu membekali kadernya dengan tiga jenis literasi:
1. Kitab Kuning (Tradisi Pesantren): Untuk memperkuat fondasi keilmuan dan spiritualitas ahlussunnah wal jamaah.
2. Kitab Putih (Ilmu Sosial dan Humaniora): Untuk memahami tantangan zaman dan membaca perubahan sosial-politik dengan jernih.
3. Kitab Abu-abu (Politik dan Strategi): Agar kader NU tidak menjadi pion dalam permainan kekuasaan global dan regional.
Tanpa perpaduan ketiganya, NU akan terjebak nostalgia sejarah, padahal lawannya bermain dengan teknologi kecerdasan buatan, jaringan think tank internasional, dan algoritma sosial media yang bisa menggiring opini publik dalam hitungan detik.
Perang Media: Jangan Tidur di Ladang Minyak
NU lambat memasuki arena digital. Kita menyaksikan bagaimana akun-akun dengan narasi keislaman intoleran, puritan, bahkan provokatif, menguasai algoritma YouTube, TikTok, dan Instagram. Para ustadz Wahabi generasi baru tampil dengan gaya kekinian, sound cinematic, dan diksi-diksi penuh percaya diri, menggugurkan otoritas kiai kampung yang bicara dengan hati dan ilmu warisan. Ini bukan perang adu benar, tapi perang merebut perhatian.
Banser dan Ansor tak bisa hanya menjadi pasukan darat; mereka juga harus menjadi pasukan udara digital, yang mampu menyebar konten hikmah, argumentasi elegan, dan klarifikasi yang menyentuh hati. NU harus menginjakkan kaki di bumi, tetapi menatap langit digital. Jangan jadikan medsos hanya tempat nostalgia ziarah dan haul, tetapi medan dakwah, pendidikan, dan penyelamatan nalar ummat.
NU Bukan Sekadar Ormas, Tapi Peradaban
Yang ingin dihancurkan bukan hanya NU sebagai organisasi, tetapi NU sebagai ruh peradaban Islam Nusantara, yang lembut tapi kokoh, tawadhu namun tegas, plural namun memiliki prinsip. Ketika Wahabi gagal mewahabikan NU secara frontal, mereka beralih dengan membelah tubuh NU dari dalam, dengan menanamkan virus permusuhan, politik identitas, dan fanatisme golongan.
Inilah waktunya NU bersatu secara strategis, bukan semata struktural. Kita tidak bisa mengharapkan semua orang punya ijazah pesantren, tapi kita bisa membentuk kader NU yang berpikir kritis, cinta damai, dan digital native. Ulama-ulama muda harus tampil bukan sebagai pemadam kebakaran, tetapi sebagai arsitek pemikiran dan pencerah zaman.
Akhir Kata: Siaga, Tanpa Paranoia
#SaveNU bukan seruan ketakutan, tetapi alarm kebangkitan. Kita tidak boleh terjebak dalam paranoia konspiratif, tetapi juga tidak bisa lagi tidur dalam kelengahan. Target tahun 2025–2030 bukan kutukan, tetapi deadline kebangkitan Nahdlatul Ulama Gelombang Ketiga.
Saatnya kita nyalakan kembali api semangat KH Hasyim Asy’ari, semangat jihad kemerdekaan, semangat cinta tanah air sebagai bagian dari iman. NU tidak boleh hanya bertahan. NU harus memimpin.
Dan satu hal yang harus diingat:
NU tidak akan bubar, jika kita sendiri tidak bubar di dalamnya.
Allāhumma ṣalli ʿalā Sayyidinā Muḥammad...
Marilah kita songsong masa depan NU bukan dengan cemas, tapi dengan cerdas dan ikhlas.