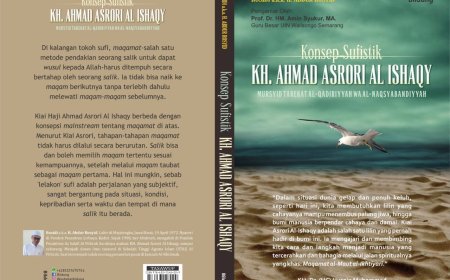Tasawuf dan Totalitas Ketuhanan
Tasawuf merupakan sebuah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mendekat kepada Allah dengan membersihkan serta menyucikan hati. Tasawuf adalah moralitas dalam Islam (Zaini, 2016). Tasawwuf memiliki metode belajar dalam kelompok belajar yang disebut tariqah. Tasawwuf mendidik manusia untuk memahami hakikat dirinya, bahwa ia adalah Abdullah atau hamba Allah yang selalu terikat dan tak pernah lepas darinya. Sebuah relasi transcendental yang kini telah memasuki era postmoderen, sebuah masa dimana manusia begitu sulit untuk membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, karena semua termanipulasi dalam banyak cara.

Tasawuf dan Rasa Cinta
Tasawuf merupakan sebuah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mendekat kepada Allah dengan membersihkan serta menyucikan hati. Tasawuf adalah moralitas dalam Islam (Zaini, 2016). Tasawwuf memiliki metode belajar dalam kelompok belajar yang disebut tariqah. Tasawwuf mendidik manusia untuk memahami hakikat dirinya, bahwa ia adalah Abdullah atau hamba Allah yang selalu terikat dan tak pernah lepas darinya. Sebuah relasi transcendental yang kini telah memasuki era postmoderen, sebuah masa dimana manusia begitu sulit untuk membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, karena semua termanipulasi dalam banyak cara.
Tasawuf kini menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghindarkan diri dari beragam manipulasi dunia. Tasawuf berfokus pada perbaikan hati, Hati merupakan sumber ketaqwaan, ketenangan, rasa takut, ketundukan, kelembutan, ketentraman, kekhusyukan, dan kesucian. Pangkal taqwa tumbuh di dalam hati yaitu dengan menjauhi kemusyrikan, kemunafikan, serta riya’ (at-Tirmidzi, 2011). Syaikh Ibn Athaillah menjelaskan bahwa manusia selayaknya memerdekakan dirinya dari segenap makhluk. Selayaknya manusia hanya bergantung pada penilaianNya, dan bukan penilaian makhluk (Ibn Athaillah, 2011). Relasi manusia dan Tuhan tidak pernah hilang, relasi transcendental ini terus menerus hidup dalam setiap peradaban manusia. Manusia meletakkan gagasan metafisika untuk memahami hakikat Yang Maha Tunggal dalam kesadaran dan pemahamannya.
Allah adalah penggerak alam semesta yang dengan itu manusia menyandarkan segenap kehidupannya kepadaNya. Relasi manusia dengan Tuhan seringkali diliputi oleh hubungan-hubungan yang berkarater transaksional, bahwa manusia menyandarkan dirinya pada Allah dalam relasi transaksi keuntungan. Bahwa kedekatan manusia padaNya tidak lepas dari motif ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya. Struktur berfikir dalam membangun epistemologi transaksional ini tidak lepas dari konsep yang dikembangkan oleh kelompok teolog yang berfikir secara legalistik.
Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya kedekatan pada Allah dapat disebabkan oleh 3 hal: kedekatan karena takut akan neraka, maka ia beribadah layaknya seorang budak yang takut akan amarah dari majikan karena kesalahan. Kedua, kedekatan karena mengharapkan pahala dan surga adalah beribadah layaknya seorang pedagang yang tengah berbisnis mengharapkan keuntungan. Ketiga, beribadah semata karena mengharap ridha Allah semata.
Hubungan yang dibangun dengan motif ekonomi berupa raihan pahala menunjukkan sebuah konsep resiprositas atau saling berbalas, untuk itulah manusia secara sadar membangun kehendaknya membangun sebuah relasi Ketuhanan yang berkarakter transaksional ini. Bahwa hal ini tidak salah, karena agama juga memberikan sebuah ruang dan kesempatan bagi manusia untuk melakukan relasi transaksi dengan Allah (Qs.[35]:29). Dalam pandangan manusia yang selalu ingin mendapatkan sebuah nilai keuntungan, maka hubungan itu adalah sah. Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk membangun sebuah relasi atas dasar muatan-muatan transaksional.
Pertanyaan yang menarik dalam hal ini adalah sejauh mana relasi bisnis ini terus dibangun oleh manusia dalam relasi transcendental ini? Lalu sejauhmanakah gagasan cinta dan keikhlasan dapat terbangun jika manusia terus membangun relasi transaksional tersebut? Allah tentunya memberikan kesempatan untuk membangun relasi transcendental ini karena Dia memahami dengan senyatanya bahwa manusia selalu berupaya memperoleh keuntungan dalam hidupnya.
Keuntungan dalam membangun bisnis dalam relasi transcendental ini mendapat kritik dari kaum pengamal tasawuf yang melihat pada sebuah kondisi ketidakikhlasan manusia membangun hubungan dengan Allah, walau tidak ditolaknya sama sekali. Kaum sufi lebih menekankan pada hubungan batiniyah dibanding hubungan-hubungan transaksional ini. Hubungan yang dibangun atas dasar cinta yang ikhlas, yang semata-mata tidak mengharapkan balasan keuntungan baik berupa pahala ataupun berupa keuntungan dunia apapun. Dalam relasi transcendental ini, kaum Sufi meletakkan Allah Sang Maha Tunggal sebagai wujud mutlak yang penuh cinta dan patut untuk dicintai secara penuh ikhlas. Al-Ghazali berupaya memurnikan relasi transcendental dari adanya unsur yang jauh dari sifat keikhlasan.
Unsur keikhlasan bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan dalam ruang manusia yang selalu meletakkan relasi transaksional transcendental ini. Selama ini manusia lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis dengan Allah. Keuntungan merupakan bentuk tujuan seseorang menjalankan hubungan-hubungan peribadatan, dan hal itu menjadi sebuah penyangga berjalannya sebuah keyakinan atas eksistensiNya. Tanpa sebuah motivasi yang bersifat keuntungan, maka sangat sulit menggerakkan manusia untuk bergerak menuju Tuhan.
Motivasi keuntungan ini terbukti sangat efektif mendorong manusia untuk bergerak menuju Tuhan, dan ketika manusia didorong oleh sebuah kekuatan spiritualisme sepenuhnya tanpa dorongan-dorongan motif keuntungan maka dibutuhkan sebuah pemahaman yang menyeluruh atas hakikat ketuhanan secara utuh. Bahwa relasi keuntungan yang digantikan oleh sebuah ide dan hasrat cinta kepadaNya bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. Lapangan manusia yang membutuhkan sebuah motivasi kebendaan harus tergantikan oleh sebuah motivasi cinta atau arrahman kepada Allah secara penuh.
Cinta sebagai Dasar
As-Syaikh ibn al-Dabbagh menjelaskan bahwa manusia cenderung mendekati sesuatu atas dasar cinta terhadapnya. Manusia tidak akan mencintai seseorang ketika ia tidak faham kesempurnaan dari orang yang aka dicintainya itu. Cinta menjadi landasan mengapa orang bersusah payah, berkorban, untuk mendapatkan apa yang ia cintai. Cinta menumbuhkan sebuah kerelaan atas segala keinginan sang kekasih, dan ia akan menutup diri dari selain yang ia cintai (al-Dabbagh, 2011). Dengan demikian motif cinta menjadi penggerak utama perilaku manusia, dan dengan motif itulah manusia mencintai Allah sebagai Zat Yang Maha Mencintai.
Tampaknya masuknya manusia ke dalam relasi sifat arrahman (Mahacinta) tanpa melihat lagi relasi transaksional menjadikannya naik pada sebuah posisi yang lebih tinggi. Manusia yang mulai meninggalkan jiwa-jiwa transaksional kepada Tuhan lalu meningkat pada relasi kecintaan dan bukan atas dasar nilai keuntungan. Tipe manusia yang sudah meninggalkan segenap keuntungan atasNya merupakan manusia khusus yang mengabdikan hidupnya kepada Allah atas motif cinta secara penuh. Hubungan ini menjadi sebuah hubungan yang begitu sempurna, karena ia membuang ego keuntungan pribadinya, dan ia hanya melihat Dia sebagai pusat dari segenap fokus hidupnya. Bukan lagi manusia yang termotivasi oleh pahala serta hadiah dari Tuhan atas segenap jerih payah yang ia lakukan selama ini.
Tingkatan ini merupakan tingkatan yang berat, manusia memulai dengan yang paling sederhana yaitu mencoba untuk mendekat dan mencoba untuk bersamaNya. Mencoba untuk meletakkan perbuatan dan berfikir berdasar pada Allah. Sesekali ia tetap meletakkan dunia yang harus dia oleh sebagai kewajibannya, tetapi semua perbuatan itu dilandasi oleh jiwa mencintai Allah Ta’ala. Bekerja dan berbuat dengan kerja keras dan bukannya meninggalkan tanggungjawabnya sebagai orang yang memakmurkan bumi (khalifah).
Bahwa ia tetap berbuat yang terbaik untuk sesamanya, untuk lingkungan alam yang ada, untuk memakmurkan segenap penduduk bumi dengan kerja keras. Tetapi disini harus secara perlahan untuk melangkah menuju Allah, bahwa niat segala hal yang dilakukannya adalah untuk menuju Allah. Tak ada lain selain hanyalah Allah sebagai motivasi gerak juangnya, bahwa Allah adalah yang ia pandang, ia melekat bersamaNya.
Bahwa ketika ia bertindak, dan bekerja selalu ia rasakan bersamaNya.
Allah memenuhi segenap jiwanya, disinilah ia meletakkan tauhid, bahwa yang hadr dalam kalbunya hanyalah Allah dan bukan yang lain. Inilah tauhid yang dikehendaki olehNya, bahwa Ia tak diduakan oleh selainNya. Manusia melangkah di jalanNya, bersamaNya, meletakkan Dia dalam qalbu terdalam. Perlahan walau berjalan tertatih ia mencoba mengejar cinta Allah selaku ar-Rahman. Jiwa manusia harus segera disegarkan kembali dengan basuhan nilai-nilai cinta ar-Rahman. Hendak kemana kita melangkah jika tidak menujuNya dan bersamaNya. Duniawi ini akan meninggalkan manusia, tetapi tidak dengan Allah. Dia sedetik dan sejengkalpun tidak pernah meninggalkan manusia. Tidak ada satupun detikpun yang mampu mengalihkanNya dari pengetahuanNya tentang manusia.
Perlu dimulai dari menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Bahwa hanya Dia adalah segenap rasa yang ada dalam hati, bahwa Dia yang menyelimuti, bahwa Dia yang menjadi pokok utama dari segenap detak jantung yang berdegup. Allah selalu bersama dan melekat dalam setiap jiwa manusia. Tidak ada kekuasaan selain kekuasaanNya, yang mengendalikan hati setiap anak manusia. Hanyalah cinta mahabbah yang melingkupi dan menyelimuti hati anak manusia. Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumiddin mengungkapkan para shalihin melepaskan dirinya dari hubungan terhadap dunia, karena segenap kesibukan yang ia lakukan dalam hidupnya adalah hanya untuk Allah (al-Ghazali, 2012). Penjelasan al-Ghazali itu tidak diartikan sebagai sikap fatalis, pasif, apatis, dan tidak peduli terhadap kehidupan dunia, tetapi lebih pada mengosongkan kalbu dari kecintaan terhadap dunia yang berlebih. Ia tetap bekerja keras, berfikir, berbuat dan bertindak, tetapi semua tindakan dan fikirnya adalah untik mengharap Allah semata, dan tidak mengharap balasan duniawi. Ini cinta kepada Allah yang telah menjadi dasar dalam hidup seorang anak manusia.
“Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada-Ku; yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah Aku fardhukan kepadanya. Hamba-Ku terus-menerus mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga Aku pun mencintainya. Bila Aku telah mencintainya, maka Aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepada-Ku, Aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepada-Ku, Aku pun pasti akan melindunginya.” [Hadits Riwayat Bukhari].
Penulis adalah Dosen Program Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia