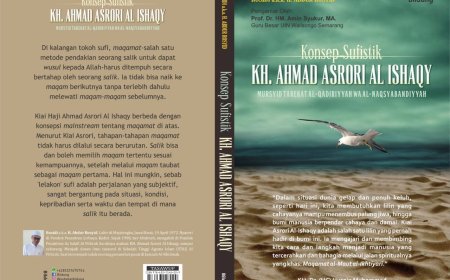SUFISME POLITIK DI NUSANTARA: SEJARAH, MANUSKRIP DAN DINAMIKA KEKUASAAN ISLAM
Habib dan Asimilasi Kekuasan

Ikhtiar Strategis Menuju Rekonstruksi Sejarah Peradaban Islam Nusantara.
Oleh: Abdur Rahman El Syarif
BAGIAN 10. HABIB HADRAMI DI PANGGUNG KOLONIAL: ANTARA ASIMILASI KEKUASAAN DAN RESISTENSI YANG DIREDAM
"Ini bukan nostalgia, ini panggilan zaman. Mari rekonstruksi sejarah peradaban Islam Nusantara sebelum semuanya lenyap dalam diam." (El Syarif 2025)
10.3. Klaim Dzurriyah Nabi dan Strategi Simbolik Kolonial: Kultus Garis Keturunan sebagai Legitimasi Baru
Dalam konteks budaya Islam Nusantara, keberadaan para dzurriyah Nabi Muhammad SAW atau yang dikenal sebagai "Habib" telah lama diposisikan sebagai simbol berkah, karisma spiritual, dan warisan kenabian, meskipun belakangan melalui kajian sejarah, filologi dan geneologi terkonfirmasi 'tidak benar' dan terus menjadi polemik berkepanjangan.
Ini menguatkan narasi bahwa entitas kelompok pendatang, lebih tepatnya didatangkan oleh penjajah kolonial Belanda sebagai rekomendasi dari hasil kajian Snouck Hurgonje terkait struktur sosial masyarakat islam pribumi nusantara.
Di banyak manuskrip pesantren Jawa dan Sumatra abad ke-17 hingga ke-19, terdapat ajaran-ajaran yang menekankan keutamaan mencintai dan menghormati keturunan Rasulullah sebagai bagian dari adab terhadap Rasul itu sendiri.^1^
Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara: 214 dan Hadis-hadis tentang Ahlul Bait sering dijadikan legitimasi spiritual atas kedudukan ini.
Kolonial Belanda, melalui strategi kultural Snouck Hurgronje, dengan cerdas memanfaatkan struktur keyakinan ini. Dalam laporan-laporannya, Snouck secara eksplisit menyatakan bahwa dzurriyah Nabi memiliki tempat istimewa di hati umat Islam, sehingga akan sangat strategis jika mereka difasilitasi untuk merebut posisi kepemimpinan agama dari tangan ulama tarekat yang cenderung politis dan keras terhadap kolonial.^2^
Pemerintah Hindia Belanda lalu menggunakan narasi kesucian garis keturunan ini untuk mendongkrak legitimasi sosial para Habib Hadhrami yang mereka angkat di berbagai kota.
Sebagai contoh, ketika Habib `Utsman bin Yahya diangkat sebagai Mufti Batavia, statusnya sebagai keturunan Nabi diumumkan secara terbuka dalam pidato-pidato resmi dan media cetak pemerintah.
Bahkan, pemerintah Hindia Belanda menyebarkan risalah yang menekankan bahwa mufti baru adalah seorang “Sayyid besar keturunan Rasulullah,” yang membawa misi keilmuan dan perdamaian.^3^
Langkah ini sangat efektif, terbukti masyarakat pribumi yang sebelumnya menaruh curiga terhadap kolaborator Belanda justru menerimanya dengan penghormatan tinggi karena dibingkai dalam aura dzurriyah.
Namun di balik itu, narasi keturunan Nabi ini juga menjadi tameng simbolik yang menyulitkan kritik. Ulama tarekat yang mencoba menentang pengaruh para Habib Hadhrami yang berafiliasi dengan Belanda kerap dituduh “tidak hormat kepada Ahlul Bait.”
Maka, politik sakralisasi keturunan ini secara tidak langsung berhasil membungkam kritik politik dan memperluas kontrol kolonial dalam balutan simbol keagamaan yang tidak bisa disentuh secara frontal.^4^
Dalam kondisi seperti ini, sufisme politik yang dahulu berporos pada karisma karamah dan kealiman ulama lokal, tergeser oleh kharisma keturunan yang difabrikasi dan difasilitasi kolonial. Ini merupakan momen penting dalam sejarah Islam Nusantara, ketika umat Islam secara perlahan diarahkan untuk memindahkan otoritas spiritual dari ulama perjuangan ke para elit keagamaan yang justru menjadi instrumen kontrol sosial kolonialisme.
Referensi:
1. Anonim, Adab al-Muridin, Tuhfat al-Mursalah ila Ruh an-Nabi, wa an-Nasihatu al-Muslimin karya ulama Jawa abad ke-18
2. Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, hlm. 71–72.
3. Snouck Hurgronje, Ambtelijke Adviezen, Vol. II, hlm. 62–65.
4. Nico Kaptein, Sayyid `Uthman of Batavia: A Muslim Scholar, Reformist and Patriot, (Leiden: KITLV Press, 1997), hlm. 44–48.
5. Laffan, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia, hlm. 94–97.