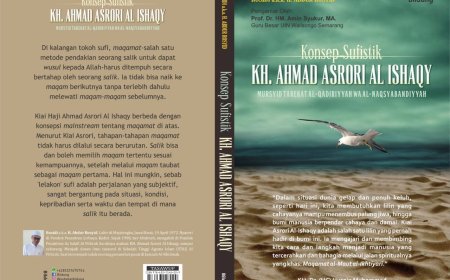Saat Alam Berbicara Dan Hati Kita Diminta Untuk Mendengar
Saat Alam Berbicara dan Hati Kita Diminta untuk Mendengar
Renungan Spiritual di Tengah Bencana 25 November 2025
Oleh:Syamsul Kamal
Bencana alam yang melanda beberapa wilayah Indonesia pada 25 November 2025 bukan sekadar peristiwa fisik; ia adalah rangkaian tanda yang mengajak manusia merenung lebih dalam. Air yang naik perlahan, angin yang mengeras beberapa detik, tanah yang bergeser apik tanpa peringatan—semuanya menciptakan suasana yang tak hanya memaksa tubuh bergerak, tetapi juga hati untuk berhenti sejenak. Dalam hiruk pikuk kehidupan modern yang sering membuat manusia kehilangan ruang kontemplasi, bencana justru menjadi jendela tempat kita menatap kembali diri dan Tuhan.
Indonesia bukan negeri asing bagi bencana. Gempa, banjir, angin kencang, dan erosi adalah bagian dari ritme alam nusantara. Namun, yang sering kita lupakan adalah bahwa setiap bencana membawa pesan tersirat. Bukan pesan yang memaksa, bukan ancaman, bukan kutukan—melainkan panggilan. Sebuah panggilan untuk mengingat, menghitung ulang langkah, dan kembali menata arah hidup.
Pada masa pandemi yang beberapa tahun lalu menggulung dunia, seorang ulama Aceh yang banyak dihormati, Wali Agama Aceh, Abuya Syech H. Amran Wali Al-Khalidi, mengucapkan sebuah kalimat yang hingga kini masih diingat banyak kalangan. Kalimat itu sederhana namun terasa seperti mengetuk pintu batin ribuan orang:
“Ingat bencana, ingat Allah.”
Kalimat ini bukan sekadar slogan, bukan kalimat pembenar situasi, bukan pula jargon keagamaan. Justru ia hadir sebagai pengingat bahwa ketika manusia terlalu yakin pada kekuatannya, terlalu percaya pada kalkulasi angka, atau terlalu sibuk mengejar kepentingan dunia, alam sering menjadi bahasa Tuhan yang paling mudah dipahami manusia.
Pesan itu kembali relevan hari ini. Bencana yang melanda tidak hanya memberi dampak fisik, tetapi juga meresonansi ke dalam hati banyak orang. Dari masyarakat di pedesaan hingga warga kota, dari kelompok relawan hingga tokoh agama, semua merasakan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh kejadian-kejadian ini.
Salah satu suara yang menguatkan renungan tersebut datang dari Syamsul Kamal, seorang jamaah yang mengikuti dakwah dan pembinaan keislaman di lingkungan MPTT-I. Ia mengatakan:
“Setiap bencana adalah panggilan halus dari Allah. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa kita ini lemah. Kita butuh Allah setiap saat, dan sering kali kita lupa.”
Dalam perspektif Syamsul, bencana bukan semata-mata derita atau musibah yang menakutkan. Ia lebih mirip pesan cinta: panggilan pelan, lembut, tetapi cukup kuat untuk menggeser hati manusia. Sebab sebagian manusia tidak akan pernah tersentuh oleh nasihat, ceramah, pidato, atau buku—namun mereka dapat tersentuh oleh peristiwa yang Allah kirimkan melalui alam.
Mengapa Bencana Bisa Menyentuh Kita?
Secara psikologis, bencana mengguncang dua hal: rasa aman dan rasa kontrol. Dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa aman karena rutinitas berjalan seperti biasa. Kita merasa mengontrol hidup karena kita bekerja, merencanakan, membeli, membangun, dan memutuskan banyak hal. Namun ketika bencana datang, semua ilusi kontrol itu dipatahkan.
Banjir tidak bertanya apakah kita sibuk.
Angin tidak bertanya apakah kita sedang mengejar target pekerjaan.
Tanah longsor tidak bertanya apakah kita sedang bahagia atau berduka.
Semua terjadi dalam satu waktu: tiba-tiba.
Dan “tiba-tiba” itulah yang sering kali menyadarkan manusia bahwa kita sebenarnya hidup dalam ketergantungan yang sangat tinggi kepada Tuhan.
Dari perspektif keagamaan, bencana adalah salah satu sarana tazkiyatun nafs—penyucian jiwa. Ia mengajarkan manusia untuk berhenti bersandar sepenuhnya pada dunia. Ia membongkar segala kesombongan kecil yang tersembunyi dalam rutinitas. Ia meruntuhkan dinding-dinding ego yang biasanya tebal.
Dalam bahasa spiritual Aceh, bencana sering disebut sebagai isyarat ilahiyah: tanda dari Allah bahwa manusia butuh kembali meluruskan arah hidupnya.
Kita Sudah Terlalu Sibuk untuk Mendengar
Manusia zaman ini hidup dalam gerak yang sangat cepat. Setiap hari dipenuhi notifikasi, deadline, pesan, target, dan tekanan sosial. Kebisingan digital membuat kita kehilangan kesempatan untuk sunyi. Dan tanpa sunyi, manusia sulit mendengar suara Tuhan.
Itulah sebabnya bencana sering menjadi satu-satunya momen ketika manusia benar-benar berhenti.
Berhenti memikirkan pekerjaan.
Berhenti memikirkan pencapaian.
Berhenti memikirkan dunia.
Dalam keadaan takut atau terancam, manusia otomatis menengok ke dalam dirinya, dan di situlah suara hati kembali aktif. Dan hati yang sadar akan kembali mengingat Sang Pencipta.
Dimensi Spiritualitas yang Sering Terlupakan
Dalam kajian ulama, bencana bukan semata-mata peringatan. Ia juga ruang penyembuhan. Bencana menghapus kesombongan, menguatkan solidaritas, memaksa manusia saling tolong-menolong, dan yang terpenting: mengembalikan manusia kepada doa.
Kita menyaksikan bagaimana saat air naik, orang saling memanggul barang satu sama lain. Saat rumah terendam, warga berbagi dapur umum. Saat listrik padam, orang saling memberi lilin. Dalam keadaan paling rapuh, manusia justru menjadi paling manusiawi.
Ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya memunculkan penderitaan. Ia memunculkan juga kebaikan, kesalehan sosial, dan kesadaran bahwa manusia butuh satu sama lain, dan semua manusia sama-sama kecil di hadapan Tuhan.
Pelajaran dari Aceh dan Sejarah Panjang Kesabaran
Aceh adalah daerah yang punya hubungan emosional dan spiritual dengan bencana. Tsunami 2004 menjadi salah satu luka terbesar bangsa ini. Namun dari luka itu, muncul pula kekuatan yang luar biasa: doa, solidaritas global, kebangkitan sosial, dan lembaga-lembaga kemanusiaan yang terus hidup hingga kini.
Masyarakat Aceh mengetahui, mungkin lebih dari daerah lain, bahwa bencana tidak selamanya tentang kehilangan. Ia juga tentang menemukan: menemukan arah baru, menemukan kedewasaan, menemukan kedekatan dengan Allah.
Itulah sebabnya pesan Abuya Amran memiliki resonansi besar di hati masyarakat Aceh. Kalimat “Ingat bencana, ingat Allah” bukan kalimat retorik, tetapi kalimat yang teruji oleh pengalaman sejarah panjang masyarakat yang berulang kali berdiri setelah jatuh.
Ikhtiar dan Tawakkal: Dua Sayap Manusia
Ulama-ulama besar selalu mengingatkan bahwa ikhtiar dan tawakkal adalah dua hal yang tak terpisahkan. Ikhtiar tanpa tawakkal membuat manusia sombong. Tawakkal tanpa ikhtiar membuat manusia pasif.
Dalam setiap bencana, masyarakat Aceh dan Indonesia membuktikan dua hal ini berjalan bersamaan:
Petugas bekerja 24 jam.
Relawan turun ke lapangan tanpa pamrih.
Warga membuka rumah bagi pengungsi.
Ulama menguatkan hati umat.
Anak-anak membacakan doa bersama, berharap kondisi cepat membaik.
Inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya: bangsa yang berjuang dan berdoa, bekerja keras sekaligus berserah diri.
Bencana Sebagai Panggilan untuk Pulang
Ketika bencana terjadi, sering muncul bisikan halus di hati manusia: “Mungkin selama ini aku terlalu jauh dari Allah.” Bisikan ini bukan rasa bersalah yang berlebihan, bukan ketakutan irasional, tetapi kesadaran bahwa manusia membutuhkan sesuatu yang lebih dari dunia: ketenangan spiritual.
Dalam bahasa para ulama, bencana adalah “tasfiyatul qalb”—pemurnian hati. Sesuatu yang membersihkan manusia dari debu-debu dunia.
Dan di detik-detik inilah manusia sering benar-benar kembali pulang kepada Allah. Bukan karena takut mati, tetapi karena menyadari bahwa hidup tanpa Allah adalah hidup yang kosong.
Penutup: Semoga Kita Mendengar Panggilan Itu
Bencana bukan hanya kerusakan fisik; ia juga sebuah dialog antara Tuhan dan manusia. Alam berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dibantah. Ia tidak menggunakan kata-kata, melainkan kejadian. Dan kejadian itulah yang seharusnya kita baca sebagai pesan.
Petuah Abuya Syech H. Amran Wali Al-Khalidi mengingatkan kita:
“Ingat bencana, ingat Allah.”
Bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Namun bagi yang pernah kehilangan, pernah hampir tenggelam, pernah merasakan tanah berguncang, atau pernah melihat air memasuki rumah, kalimat itu adalah cahaya. Ia bukan menakutkan, tetapi menenangkan. Ia bukan menyudutkan, tetapi memeluk.
Dan seperti dikatakan Syamsul Kamal:
“Allah tidak menghukum. Allah hanya mengingatkan. Dan manusia hanya perlu mendengar.”
Semoga bencana hari ini tidak kita baca sebagai malapetaka belaka. Semoga ia kita baca sebagai nasihat. Sebagai isyarat. Sebagai cara Allah menuntun kita untuk kembali. Semoga Allah menjaga Aceh. Semoga Allah menjaga Indonesia.Semoga Allah menjaga hati kita yang sedang belajar pulang.
Aamiin.