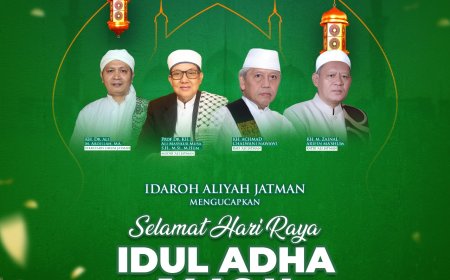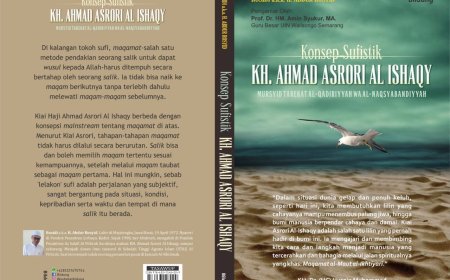Sikap Proporsional terhadap Khilafiyah Ucapan Natal

Ada yang terasa kurang nyaman terdengar ketika mendengarkan khutbah jumat siang tadi di Masjid tempat saya tinggal, yang bertemakan hukum mengucapkan Hari Raya Natal bagi seorang muslim.
Tema ini selalu ramai diperbincangkan tiap tahun pada waktu-waktu seperti saat ini yang tinggal menghitung hari datangnya perayaan Hari Natal. Sebetulnya, sah-sah saja menyampaikan materi seperti itu dalam khutbah Jumat, asalkan Sang Khatib bersikap proporsional, berimbang, dan bijak. Karena, jamaah yang hadir pasti juga menganut pandangan yang beragam, termasuk berbeda pandangan dengan Sang Khatib.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hukum mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi seorang muslim itu masih diperdebatkan hukumnya dikalangan para ulama (khilafiyah). Ada yang membolehkan sehingga tidak haram hukumnya mengucapkannya, dan ada pula yang tidak membolehkan sehingga hukumnya haram mengucapkannya. Sang Khatib tadi begitu semangat memaparkan berbagai dalil baik dari al-Quran, pendapat ulama, termasuk merujuk pula Fatwa MUI tahun 1981, yang pada intinya mengatakan haram hukukmnya mengucapkan Hari Raya Natal bagi seorang muslim. Bukan saja hukumnya yang haram, orang yang mengucapkannya pun menjadi kafir/musyrik, kata Sang Khatib dengan cara penafsiran yang menurut hemat saya terlalu jauh keluar dari metode dan logika penalaran keilmuan. Tapi tidak masalah, toh saya tetap menghargai pendirian/pendapat Sang Khatib itu karena saya tau memang ada sebagian ulama juga yang berpendapat demikian, sehingga jika Sang Khatib mengikuti kelompok ulama yang demikian sah-sah saja. Hanya saja yang kurang tepat/kurang bijak menurut saya, Sang Khatib dalam menjelaskan tema itu terlihat memberikan justifikasi (penghukuman) seakan-akan tidak ada ulama lain lagi yang membolehkan dan tidak menghukumi haram mengucapkan selamat Hari Raya Natal itu, atau seolah hal itu bukanlah suatu masalah yang tidak diperdebatkan di kalangan para ulama.
Kenapa demikian, karena Sang Khatib sama sekali tidak memberikan penjelasan secara komprehensif/utuh kepada jamaah mengenai adanya pendapat ulama lain yang juga tidak melarang atau memghukumi boleh mengucapakannya. Saya cukup mencermati secara kritis isi materi khutbah Sang Khatib selama khutbahnya berlangsung. Sempat terlintas pula fikiran penyesalan akan cara khutbah Sang Khatib itu, bahkan dalam hati berkata, “Kok, Khatib ini aga takabur seperti merasa mengerti sendiri dan kita sebagai jamaah ini tidak tau apa-apa.” Tanpa sadar terlihat pula beberapa jamaah sekitar yang saya duga mungkin mereka juga sedang mengalami suasana seperti yang saya alami, bahkan boleh jadi ditambah dengan sedikit kebingungan, karena mungkin saja mereka termasuk orang yang sering mengucapkan selamat natal ke temannya, saudaranya, atau tetangganya. Dengan kata lain, mereka merasa terhakimi telah menjadi orang kafir/musyrik karena pernah mengucapkan selamat Natal. Cuma ya… namanya khutbah kan beda dengan seminar, diskusi. Jamaah hanya bisa menjadi pendengar yang baik dan tidak bisa berkomentar apa-apa (sami’na, meskipun belum tentu wa’athona, jika isi khutbahnya keliru atau mungkin mengenai masalah yang masih diperdebatkan). Bahkan, hukumnya haram dan sholat bisa menjadi batal gara-gara berbicara. Karena tidak bisa berdebat/mengajukan tanggapan, saya hanya berfikir dan timbul ide sekaligus harapan kiranya masalah-masalah khilafiyah semacam ini tidak perlu menjadi tema-tema khutbah Jumat, jika mau dibuatkan forum diskusi tersendiri yang bersifat dua arah. Kalaupun tetap menjadi tema khutbah Jumat juga, lebih bijak jika khatib dapat menjelaskan secara objektif/utuh mengenai permasalahannya termasuk penjelasan mengenai perbedaan sikap/pendapat para ulama terhadap masalah itu.
Meskipun nantinya Sang khatib menyampaikan pendiriannya terhadap pendapat para ulama tertentu, tapi Sang khatib jangan sampai terkesan menggurui/mendoktrin jamaah untuk mengikuti pendapatnya saja, apalagi yang lebih keliru menutupi atau tidak mengungkap pandangan ulama lainnya yang berbeda itu, hanya demi menonjolkan pendapat pihak yang diikuti sehingga terkesan hanya ada satu pendapat dan itulah yang mutlak. Jika terjadi demikian, maka mimbar Jumat hanya akan menjadi instrumen/alat monopoli faham-faham kelompok tertentu yang memiliki faham keagamaan yang berbeda dengan jamaah lainnya, yang tentu saja tidak mesti terjadi dan sangat disayangkan. Yang dikhawatrikan lagi, jamaah yang tidak sependapat dengan Sang Khatib bisa jadi sholatnya kurang khusyu karena sibuk memikirkan ceramah Sang Khatib. Saya jadi penasaran dengan Sang Khotib yang merujuk Fatwa MUI tahun 1981 tadi, sampai terlintas pertanyaan dalam hati apa Sang Khotib tadi pernah membaca secara cermat Fatwa MUI itu? Kebetulan saya mengkoleksi himpunan Fatwa MUI yang berisi fatwa-fatwa MUI termasuk di dalamnya fatwa tentang masalah natal yang dirujuk Sang Khatib tadi, yang telah saya baca beberapa tahun lalu. Karena, seingat saya memang fatwa itu tidak menyebutkan soal haram hukumnya mengucapkan selamat Hari Raya Natal, namun mengenai haram hukumnya merayakan Hari Raya Natal. Namun, karena saya tidak ingin takabur dengan apa yang saya ingat, serta menghindari prasangka macam-macam kepada Sang Khatib yang merujuk Fatwa MUI itu, saya fikir nanti sajalah saya memastikannya lagi ketika sudah kembali ke rumah. Bukan apa-apa, etika keilmuan Islam mengajarkan perlunya kehati-hatian, kecermatan, akurasi dalam pengutipan suatu sumber, tidak bisa asal kutip sana sini tanpa akurasi data yang tepat/benar, apalagi memanipulasi sumber, bisa dicap sebagai ketidakjujuran/ketidakadilan intelektual.
Karena rasa penasaran, sesampainya di rumah, saya langsung mengambil Himpunan Fatwa MUI itu yang karena cukup tebal tidak sulit untuk menemukannya. Setelah dilihat ternyata betul memang Fatwa MUI itu tidak membicarakan masalah hukum mengucapkan selamat hari natal, apalagi mengharamkannya sebagaimana yang dikatakan Sang Khatib tadi. Artinya Sang Khatib tadi sudah jelas keliru dalam mengutip referensi sebagai dasar/argumen materi khutbahnya. Bunyi fatwa itu demikian: “Mengikuti upacara Natal Bersama bagi umat Islam hukumnya haram”. Tentu saja, mengikuti upacara Natal bersama dengan mengucapkan selamat Hari Raya Natal merupakan dua hal yang berbeda jauh. Tidak sampai disitu, saya juga ingat beberapa tahun lalu keluarga Buya Hamka pernah mengklarifikasi mengenai hal ini karena merasa ada kesalahfahaman ditengah masyarakat, seolah Buya Hamka pernah memfatwakan haram hukumnya mengucapkan selamat Hari Raya Natal oleh seorang muslim. Maklum, Fatwa MUI itu memang diterbitkan Ketika Buya Hamka Menjabat sebagai Ketua MUI. Dari hasil penelusuran saya di internet, ternyata benar, salah satu cucu Buya Hamka mengatakan Buya Hamka bukan melarang umat Islam mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Akan tetapi, lebih kepada ikut perayaan Natal bersama orang-orang Kristiani. Cucu Buya Hamka itu bahkan menceritakan bagaimana hubungan keluarga Buya Hamka dengan tetangganya umat kristiani saat merayakan natal. Keluarga Buya Hamka bahkan terbiasa membuat kue dan mengantarkannya kepada para tetangga yang merayakan Natal sekaligus untuk memberikan ucapan selamat merayakan Natal.
Saya pun membuka referensi lain yang sudah lama saya baca, antara lain terjemahan buku Fiqh Minoritas yang berisi kumpulan fatwa kontemporer karya Yusuf al-Qardhawi, Penerbit Zikrul Hakim, tahun 2004, pada halaman 206 dan 207, disebutkan:
“Akan tetapi, menurut saya tidak masalah seandainya kaum muslimin ingin memberikan ucapan terhadap hari raya mereka, apalagi di antara keduanya (muslim dan non muslim) terdapat hubungan kerabat, tetangga, teman dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang membutuhkan rasa cinta, kasih sayang dan hubungan yang baik, yang biasa berlaku dalam tradisi masyarakat yang sehat”
Syekh Yusuf Al-Qardhawi juga memberikan komentar atas pendapat Ibnu Taimiyah yang pernah mengharamkan ucapan natal ini dengan mengatakan:
“Seandainya Ibnu Taimiyah hidup sampai pada zaman di masa kita hidup sekarang dan melihat semua kenyataan ini, niscaya ia akan mengubah pendapatnya. Atau setidaknya memperingan isi fatwanya, karena sebagai seorang mujtahid ia sangat memperhatikan tempat, waktu dan kondisi di mana fatwa tersebut dikeluarkan”. Hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqih yang artinya: “Hukum itu berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebisaaan”
Jadi tambah heran saya dengan Sang Khatib tadi, kok, berani sekali bisa menghukumi kafir/musyrik bagi orang yang mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Artinya, Syekh Yusuf al-Qardhawi, Sang Ulama yang diakui kelimuannya secara internasional itu ikut pula dihukumi kafir/musyrik terkait pendapatnya di atas.
Akhirnya, saya hanya dapat berharap untuk tema-tema yang bersifat khilafiyah, sebaiknya tidak disampaikan dalam mimbar khutbah (kalau mau, dibuat forum diskusi sendiri yang bersifat dua arah). Kalaupun disampaikan juga, Sang Khatib harus bersikap bijak, proporsional, berimbang informasinya, dan menghindari kesan monopoli, doktrinasi pendapat keagamaan tertentu kepada jamaah, yang justru tidak sehat, tidak kondusif bagi persatuan antar jamaah masjid yang beragam faham keagamaannya. Ini bukan saja dalam mimbar khutbah tapi termasuk ceramah-ceramah lainnya. Karena jika tidak, dikhawatirkan masjid yang tadinya harus menjadi sarana penguatan persatuan, soliditas ummat (selain ibadah ritual), justru sebaliknya bisa menjadi sumber konflik pemecah belah ummat akibat kekeliruan menyikapi perbedaan pendapat. Kata seorang Ahli tafsir, “Yang menjadi masalah itu bukan perbedaan, tapi cara menyikapi perbedaan itu”. Firman Allah: Aliimun Hakiim (Maha Mengetahui dan Bijaksana). Ilmu saja tidak cukup, tapi perlu juga kebijaksanaan. Wallahu Alam Bishawab. []