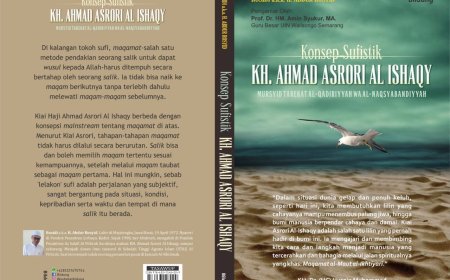Mengawal Otoritas Agama di Ruang Publik

Jakarta, JATMAN Online – suatu pemberitaan, ada seorang ustaz mengharamkan merk air mineral tertentu yang dibawa ke majelis taklim karena merupakan produk asal Prancis, yang dianggap negeri orang “kafir.” Video sang ustaz yang kurang tiga menit itu diunggah sebuah akun instagram akhir 2020, ditonton lebih dari 34.000 kali dalam 7 jam setelah penayangan.
Maret 2022 ini, pernyataan yang sama kembali viral, juga melalui media sosial. Banyak kritik atas aksi pengharaman ini, tapi tak sedikit yang mendukungnya.
Terakhir bulan Oktober 2022 muncul kasus wanita bercadar bernama Siti Elina mencoba menerobos ke istana negara sambil membawa senjata api dengan misi sebagai jihad. Cara pandang dan perilaku sosial keagamaan ini dipengaruhi oleh pemahaman keagamaannya.
Aksi ini sejatinya adalah fenomena pemahaman keagamaan yang persoalannya tidak sederhana. Ini semacam gunung es mengenai persoalan eksistensi otoritas agama di ruang publik yang patut dicermati kembali. Tak sedikit wacana keagamaan—yang karena kompeksitasnya—sama sekali ‘tak cukup’ diselesaikan melalui perdebatan tanpa arah dalam keterbukaan dan kebebasan bermedia.
Tapi benarkah otoritas agama yang kompeten dan bersedia mengawal tumbuh kembang Islam moderat dan persistensi demokrasi tak lagi menarik jadi rujukan? Bagaimanakah ormas Islam moderat sebaiknya merespons fenomena kontestasi gagasan keagamaan yang kerap kali memunculkan isu-isu berbahaya bagi kehidupan berbangsa?
Kontestasi Ideologi di Ruang Publik
Ruang publik media digital mengubah gaya hidup masyarakat dalam banyak aspek, termasuk bidang agama. Kemudahan, kecepatan akses dan kebebasan berekspresi di media digital menjadi pemandangan biasa hari ini. Meski memiliki nilai positif, penggunaan media sosial untuk menyampaikan apa saja, cenderung kurang disadari bahayanya baik bagi individu maupun masyarakat luas. Para ahli, seperti Fuchs (2014), mengingatkan betapa media sosial merupakan ruang eksploitasi kapitalisme jenis baru yang kurang atau bahkan tidak disadari.
Dalam konteks keberagamaan, kehadiran dan penggunaan teknologi informasi yang massif ini mendorong terjadinya kontestasi terbuka berbagai paham dan ajaran. Sekitar tahun 1980-an, untuk mendapatkan pengetahuan agama dan mengkonfirmasi interpretasi ajaran—dalam berbagai aspek—masyarakat merujuk kepada ulama dan ormas tertentu yang teruji kompetensinya. Otoritas agama yang disematkan pada ulama sebagai rujukan ini teruji bukan oleh hal-hal di luar kapasitas dirinya. Tapi belakangan, rujukan itu bergeser. Media, khususnya media sosial, menjadi tempat efektif untuk belajar agama.
Riset Alexander R. Arifianto (2020) menunjukkan bahwa menguatnya paham keagamaan eksklusif dan cenderung intoleran diakibatkan minimal oleh dua hal. Pertama, menguatnya interaksi dan saling pengaruh gagasan, ide, pandangan dan ajaran secara terbuka.
Mengutip John Stuart Mill, ia menyebutkan bahwa pasar gagasan ini (marketplace of ideas) diekspresikan secara terbuka melalui diskusi atau pengajian. Sejauh logika pasar, kontestasi gagasan pun berjalan terbuka, fair, bebas dan sepenuhnya ditentukan oleh dominasi pendukung dan pengikut. Gagasan yang dianggap lemah dan oleh pasar dinilai tak menjual akan tersingkir. Kedua, munculnya figur publik, khususnya di media, yang dinilai memiliki daya tarik tersendiri dan mendapatkan tempat di kalangan masyarakat. Tokoh-tokoh populer inilah yang oleh Muhammad Qosim Zaman (2002) disebut sebagai ‘cendekiawan agama baru’. Mereka lahir secara instan melalui ruang publik digital. Ironisnya, tak sedikit yang muncul berbarengan dengan kelompok-kelompok Islam pembawa semangat eksklusif.
Bagi mereka yang baru belajar agama kehadiran tokoh-tokoh populer tersebut cenderung sangat memikat setidaknya karena dua hal. Pertama, paham yang diajarkan dinilai, atau dianggap baru dan seolah memenuhi dahaga spiritual di tengah kompleksitas masalah hidup yang memang cenderung mencerabut manusia dari jati diri.
Fenomena hijrah—yang kemudian diamplifikasi oleh keterlibatan kalangan selebritas—misalnya, menggambarkan situasi ini. Kedua, penggunaan media sosial yang efektif membuat tokoh-tokoh atau ‘cendekiawan agama baru’ ini mudah diakses publik. Hubungan tokoh dan audiens menjadi terasa intens. Jarak dipangkas habis. Biaya pun dianggap murah. Lalu kemasan, gimmick marketing, dan berbagai aspek yang memungkinkan setiap pesan bisa dengan mudah diterima serta menjangkau khalayak di berbagai level usia maupun strata sosial, memainkan perannya.
Otoritas agama yang lahir dari riuhnya media sosial ini, mungkin tampak tidak secara vulgar melakukan perlawanan terhadap paham keagamaan yang ramah sebagaimana menjadi karakter utama kalangan di ormas keagamaan. Namun seringkali juga tampak jelas basis ideologi dan pemikirannya mengandung spirit salafi.
Ekspresi anti tradisi dari para tokoh agama populer ini berkali-kali menyeruak dan menjadi kontroversi. Tak jarang pula gejala itu muncul dalam bentuk pernyataan ‘serampangan’ seperti dalam kasus pengharaman dua merk minuman mineral karena merupakan produk ‘orang kafir’. Atau penyampaian materi ceramah keagamaan yang menoleransi tindakan kekerasan dan intoleran.
Di level yang lebih mengerikan adalah ketika gejala-gejala paham keagamaan eksklusif ini dimainkan di arena politik. Jelas, kita sudah cukup melihat pemandangan ini terjadi dalam bebeberapa tahun terakhir.
Memang, tak sedikit juga tokoh atau kalangan moderat dan inklusif juga memaksimalkan penggunaan media sosial. Tapi perimbangannya belum cukup. Berbagai penelitian menunjukkan betapa massifnya penggunaan media sosial sebagai alat penyebaran isu-isu keagamaan yang mendorong lahirnya sentimen anti keberagaman dan toleransi. Bahkan menjadi alat rekerutmen dalam Gerakan radikalisme-terorisme.
Dunia maya menjadi ruang inkubasi ajaran-ajaran intoleran yang kemudian tumbuh subur melalui suara otoritas agama minus kapasitas, tapi memiliki banyak penggemar dan pengikut.
Bahkan aktivis keagamaan yang sudah dikenal aktif menyebarkan Islam garis keras, juga terang-terangan menjadi bagian dari kontestasi ini. Hingga terjadilah antara lain apa yang disebut Nestor Garcia Canclini (1990) sebagai hibridisasi budaya (cultural hybridization), yaitu upaya individu atau kelompok untuk mengadopsi ajaran atau paham baru untuk bisa melindunginya dari tekanan budaya atau paham yang dianggap bertentangan. Jika kekuatan dunia digital dan ramuan ‘pesan agama’ yang dimainkan “cendekiawan agama baru” tidak diimbangi gerakan keagamaan bernalar, risikonya cukup serius.
Hemat penulis, kelompok keagamaan yang tersebar di masyarakat seperti ormas keagamaan semacam NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, NW dan selainnya belum cukup agresif melakukan perimbangan, bahkan jika perlu menguasai medan pertarungan ideologi melalui improvisasi dan inovasi teknologi dunia digital.
Ketika metode dan pendekatan kegiatan keagamaan kalangan intoleran, bahkan radikalis begitu kuat memanfaatkan teknologi informasi mutakhir, ormas keagamaan secara umum masih menggunakan pendekatan-pendekatan konvensional.
Tak diragukan banyaknya aktor yang mengutuk dan meluruskan paham-paham Islam destruktif di ‘daratan’, sementara perang sesungguhnya terjadi di dunia maya.
Reposisi Pendekatan Dakwah
Bagaimana peran dan posisi ormas Islam dalam merespons perubahan ruang publik yang semakin pesat ini? Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, lembaga ormas Islam perlu bersinergi untuk merumuskan pendekatan dan strategi dakwah di ruang publik secara massif dan relevan.
Penting bagi kedua ormas ini bekerjasama dan berdampingan untuk menghadapi ‘musuh bersama’ dalam bentuk paham keagamaan yang dangkal, bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedua, Lembaga ormas Islam perlu membuat jaringan dan ruang-ruang publik di dunia digital yang adaptif dengan generasi milenial. Ada ruang untuk cara-cara konvensional, tapi penguatan peran di media digital merupakan keniscayaan.
Memfokuskan pada isu dakwah konvensional dan kegiatan ritula oleh ormas Islam ini perlu juga dibarengi dengan penguatan rekayasa teknologi dalam dunia informasi.
Reposisi dakwah harus dilakukan dalam keseluruhan aspek, baik itu alat, skill, juga tentu budaya kerja-kerja dakwah. Masukan ini mungkin sederhana dan bisa dianggap klise.
Tapi jika diturunkan dalam rincian strategi dan direalisasikan secara serius, upaya-upaya untuk menjaga Indonesia sebagai rumah bagi Islam toleran dan moderat akan sangat terbantu.
Penulis: Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D (Direktur Sekolah Pascsarjana UIN Jakarta)