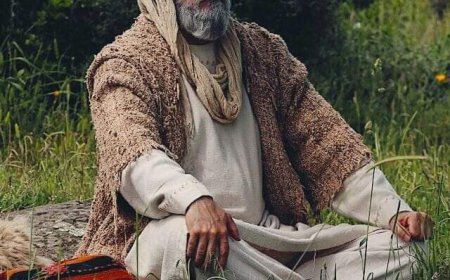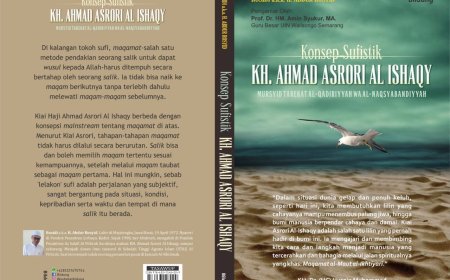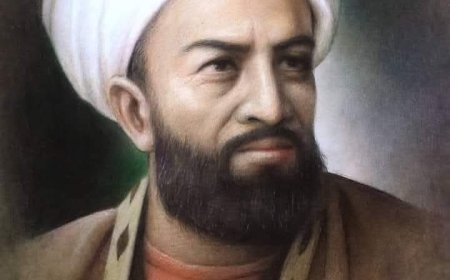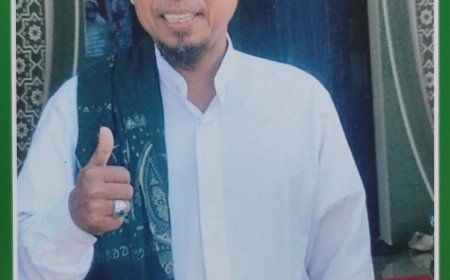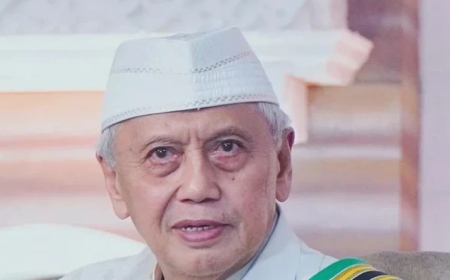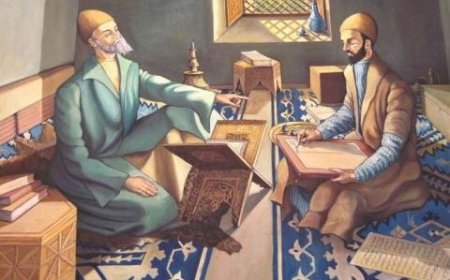Integrasi Tasawuf dalam Institusi Negara: Solusi Krisis Etika Aparat dan Moral Governance

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara—seperti kasus Brimob menabrak driver ojek online hingga tewas—menjadi cerminan krisis spiritual dan kemanusiaan dalam institusi negara, menandakan lemahnya integrasi antara dimensi batin (tasawuf) dan fungsi formal negara (Taher et al., 2025). Tasawuf, sebagai dimensi spiritual Islam, menawarkan kerangka etis dan moral yang dapat memperkuat integritas lembaga negara sebagai entitas yang tidak hanya procedural, tetapi juga beradab (Ernst, 2020). Integrasi ini menjadi penting agar aparat negara tidak hanya taat hukum, tetapi juga berperikemanusiaan.
Taher et al. (2025) menyajikan kerangka konseptual bagaimana ajaran etika Sufi—seperti ikhlas, amanah, dan adl—membentuk perilaku etis dan integritas organisasi melalui kesadaran spiritual sebagai mediator utama. Dalam konteks institusi negara, prinsip-prinsip ini dapat menjadi fondasi moral yang meneguhkan kepemimpinan yang transparan dan bertanggung jawab.
Buku Modern Sufis and the State menyajikan kisah-kisah Sufi yang berinteraksi dengan politik di Asia Selatan, menolak stereotip bahwa Sufisme hanya bersifat pasif atau apolitis. Justru, keterlibatan Sufi dalam ranah politik dapat menawarkan alternatif nilai dalam sistem pemerintahan yang inklusif dan toleran (Ewing dan Corbett, 2020).
Namun, seperti diingat oleh sejumlah analis kritik, Sufisme juga bisa menjadi pedang bermata dua: terkadang membawa toleransi, tetapi bisa juga menyuburkan pasifisme politik ("quietism") yang meminggirkan peran kritis dalam reformasi institusional (Akhlaq, 2023). Ini menjadi tantangan dalam merancang integrasi spiritual yang autentik, bukan sekadar ritual simbolik.
Ismail Raji al‑Faruqi dalam Al‑Tawḥīd: Its Implications for Thought and Life menekankan bahwa konsep Tauhid merupakan fondasi etika, sosial, dan politis dalam Islam—menjembatani spiritualitas dan struktur sosial-material negara melalui konsep keadilan, kepemimpinan yang adil, dan kesadaran kolektif (Al-Faruqi, 2000). Integrasi ini sangat relevan untuk mempertebal dimensi etis dalam aparatur negara.
Syed Muhammad Naquib al‑Attas menawarkan pendekatan Islamisasi pengetahuan. Ia menegaskan bahwa integrasi antara ilmu formal dan ilmu tasawuf adalah prasyarat pembangunan spiritual dan intelektual umat (Mudin dan Desnafitri, 2019). Dalam konteks lembaga negara, pendekatan ini memperkuat kapasitas moral aparatur melalui pelatihan berbasis spiritualitas mendalam.
Studi Taher dkk. menekankan bahwa spiritual consciousness (kesadaran batin dalam Sufisme) mengkatalisasi kepemimpinan inklusif, kohesi sosial, dan moral governance dalam perusahaan (Taher et al., 2025). Jika ditranslasikan ke lembaga pemerintahan, hal ini dapat membentuk birokrasi yang manusiawi dan empatik, sekaligus disiplin dan akuntabel.
Peristiwa penabrakan oleh aparat Brimob terhadap seorang pengemudi ojol merupakan puncak krisis etika: hilangnya kepekaan kemanusiaan, kurangnya empati, serta dominasi naluri kekuasaan tanpa kendali spiritual. Hal ini melambangkan ketidakharmonisan antara kekuatan institusional dan ruhani moral.
Integrasi tasawuf dalam lembaga negara bukan sekadar formalitas; diperlukan pelatihan intensif yang menanamkan nilai ikhlas, amanah, 'adl, dan introspeksi spiritual. Ini dapat membentuk aparat yang tidak hanya disiplin, tetapi juga empatik.
Mengembangkan instrumen pendidikan aparatur yang mencakup modul tasawuf—seperti zuhud, taubat, tadabbur—dapat meningkatkan kesadaran spiritual yang mengatur perilaku di lapangan. Memang, hal ini diperlukan riset empiris untuk mengukur efektivitas pelatihan spiritual terhadap perilaku aparat—misalnya sebelum dan sesudah pelatihan dilihat indikator empati, disiplin, serta akuntabilitas.
Diperlukan kebijakan kelembagaan yang mendorong praktik spiritual, seperti refleksi rutin, diskusi etis, dan pendekatan holistik dalam penilaian kinerja aparat—bukan hanya dari aspek tugas, tetapi dari kedalaman moral juga. Perlu diingat, pendekatan spiritual bisa jadi dianggap "kosmetik" jika tidak diikuti komitmen nyata dari pimpinan. Oleh karena itu, pembinaan perlu dilakukan secara konsisten dan otentik.
Integrasi tasawuf dalam lembaga negara memberikan potensi transformasi moral yang mendasar: memperkaya dimensi manusiawi aparat, memperkuat etika kelembagaan, dan menumbuhkan tanggung jawab spiritual. Kasus Brimob–OJOL menjadi tanda bahwa paradigma hukum saja tidak cukup; perlu keseimbangan dengan kedalaman spiritual agar negara benar-benar melayani rakyat dengan keadilan dan empati.
Referensi:
- MSIM Taher et al., “The Role of Sufism in Shaping Ethical Practices and…,” Atlantis Press, 2025. DOI 10.2991/978-94-6463-827-1_5
- Ernst, Carl W., “Ambiguities and Ironic Reversals in the Categorization of Sufism “ dalam Modern Sufis and the State, Columbia University, 2020.
- Ewing, Katherine Pratt, et Rosemary R. Corbett, dir. Modern Sufis and the state: the politics of Islam in South Asia and beyond. Religion, culture, and public life. New York : Columbia University Press, 2020.
- Isma’il Raji al‑Faruqi, Al‑Tawḥīd: Its Implications for Thought and Life, International Institute of Islamic Thought, 1982.
- Mudin, Moh.Isom, et Andin Desnafitri. “Al-Attas on Intelect and It’s Relevance to The Islamization of Knowledge: Sufism philosophical Approach”. Khatulistiwa 9, no. 2 (2020) : 5‑19. https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v9i2.1479.