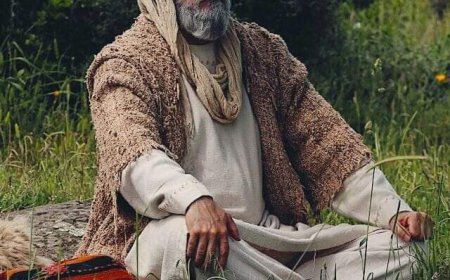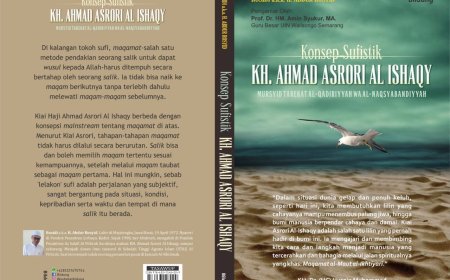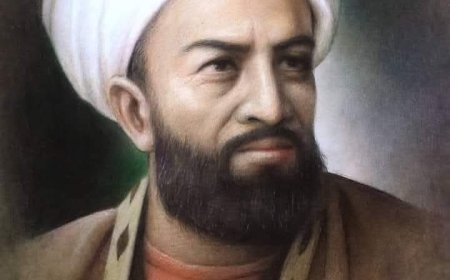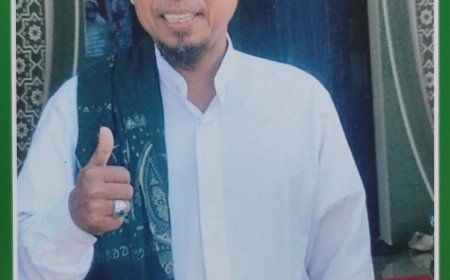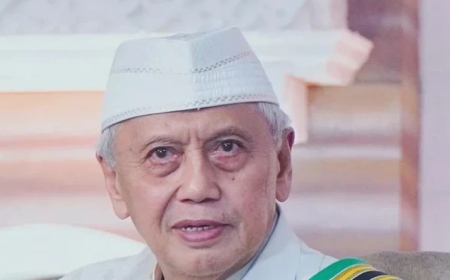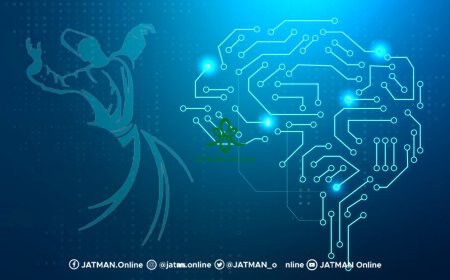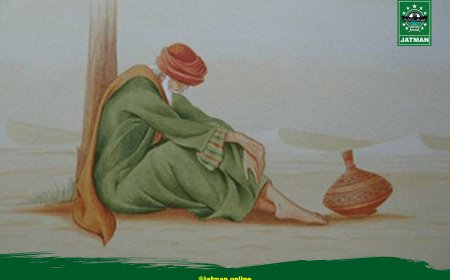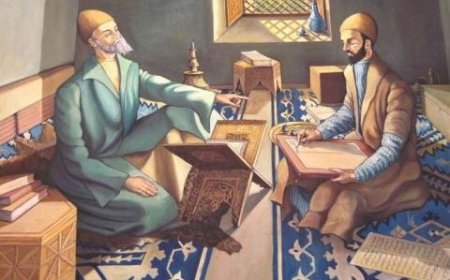Arabisme dan Bahasa Orang-orang Surga: Memahami Makna Bahasa Arab dalam Islam
Bahasa Arab

Arabisme dan bahasa Orang-orang surga (freepik). Amien Nurhakim Penulis Download PDF Bahasa Arab telah lama memikat hati umat Muslim di seluruh dunia, tidak hanya karena perannya sebagai bahasa Al-Qur’an dan hadits, tetapi juga karena keyakinan yang tersebar luas bahwa bahasa ini memiliki kedudukan istimewa di akhirat. Banyak umat Muslim termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab dengan penuh semangat, didorong oleh narasi bahwa bahasa ini adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk surga.
Sehingga, motivasi sebagian umat Muslim mempelajari bahasa Arab bukan sekadar keterampilan linguistik, melainkan juga upaya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Motivasi ini tampak jelas dalam berbagai lingkungan pendidikan Islam, mulai dari pesantren hingga komunitas Muslim di negara-negara non-Arab. Bahasa Arab dipandang sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran agama, sekaligus sebagai tiket untuk “berkomunikasi” dalam suasana surga kelak. Faktanya, umat Muslim tersebar di berbagai penjuru dunia, dari Asia Tenggara hingga Afrika, Eropa, dan Amerika, dengan latar belakang bahasa dan budaya yang sangat beragam. Tidak semua Muslim memiliki akses atau kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab, apalagi menguasainya.
Di antara umat Muslim, ada yang menjalani hidup dengan penuh ketaatan, namun hanya berkomunikasi dalam bahasa ibu mereka. Jika bahasa Arab benar-benar bahasa penduduk surga, apakah ini berarti ada ketimpangan spiritual bagi mereka yang tidak menguasainya? Lantas, bagaimana dengan nasib umat Muslim yang seumur hidup tidak pernah mempelajari bahasa Arab? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu merujuk literatur yang menampilkan pernyataan bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab, yaitu sebuah riwayat yang diklaim sebagai hadits Rasulullah, yaitu:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ: لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ A
rtinya, “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, ‘Cintailah orang-orang Arab karena tiga hal: karena aku adalah orang Arab, Al-Qur’an berbahasa Arab, dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab’.” (HR At-Thabarani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir, [Mosul, Maktabatul ‘Ulum wal Hikam: 1983], jilid II, halaman 185). Riwayat di atas, jika diterima begitu saja sebagai otoritas agama, dapat dipahami seolah-olah meninggikan satu Bahasa, dan bahkan satu ras, di atas yang lain. Dengan menyatakan bahasa Arab sebagai bahasa surga, secara tidak langsung bahasa dan budaya lain bisa terkesan diposisikan sebagai “kelas dua". Riwayat ini menciptakan hierarki yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Lantas, bagaimana pandangan para ahli kritik hadits terhadap riwayat ini? Al-Haitsami mengomentari ada sosok perawi yang disepakati dha’if periwayatannya dalam sanad hadits di atas, yaitu Al-‘Ala bin ‘Amr al-Hanafi:
رواه الطبراني في الكبير والاوسط إلا انه قال ولسان أهل الجنة عربي، وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه
Artinya, “Hadits ini diriwayatkan oleh At-Thabarani dalam kitab Al-Mu’jam Al-Kabir dan Al-Ausath, namun dalam riwayatnya disebutkan dengan lafal ‘bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab’. Dalam sanadnya terdapat Al-‘Ala bin ‘Amr al-Hanafi, yang telah disepakati sebagai perawi yang dha’if (lemah) periwayatannya.” (Majma’uz Zawaid, [Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyah: 1988], jilid III, halaman 108). As-Suyuthi dalam Jami’ul Ahadits juga menginformasikan bahwa Ad-Dzahabi mengaggap hadits ini maudhu’ alias palsu. Al-‘Uqaili menilainya sebagai hadits yang munkar dan tidak memiliki asal (la ashla lahu), sedangkan Ibnul Jauzi meletakkan hadits ini dalam karyanya yang berjudul Al-Maudhu’at, atau ensiklopedia hadits-hadits palsu. Keterangan ini juga disampaikan oleh Muhammad bin Darwisy Al-Haut, ulama terkemuka Beirut era Dinasti Utsmani:
متكلم فيه قال الذهبي فيه محمج بن الفضل متهم وقال أظن الحديث موضوعاً وعن ابن حبان أنه موضوع وعن أبي حاتم فيه كذاب
Artinya, “Perawi hadits ini dipermasalahkan. Adz-Dzahabi mengomentari hadits ini, ‘Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al-Fadhl, ia dituduh (sebagai pemalsu hadis).’ Dan ia juga berkata: ‘Saya kira hadis ini mawdhu' (palsu).’ Ibnu Hibban juga menilai hadits ini sebagai mawdhu’ (palsu). Sementara Abu Hatim mengomentari perawi tersebut, ‘Ia adalah seorang pendusta’.” (Jami’ul Ahadits, jilid I, halaman 477; dan Asnal Mathalib fi Ahadits Mukhtalafatil Maratib, [Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyah: t.t.], jilid I, halaman 31).
Penjelasan ulama mengenai hadits Hadits ini secara gamblang merupakan sebuah riwayat yang dikaitkan dengan perintah untuk mencintai bangsa Arab. Alasannya merujuk kepada tiga hal: Karena Nabi adalah orang Arab, sehingga dapat dipahami bahwa keterangan ini mengacu pada identitasnya sebagai bagian dari bangsa Arab, baik dari segi bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Arab yang fasih, maupun dari segi nasab yang menyatukan mereka. Karena Al-Qur’an berbahasa Arab.
Keterangan ini menunjukkan keistimewaan bahasa Arab sebagai wahana penyampaian Al-Qur’an, yang terkenal akan kefasihan, keindahan, dan keunggulan gaya bahasanya. Karena bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Keterangan ini merujuk pada bahasa yang digunakan oleh para penghuni surga, siapa pun itu, termasuk manusia dari generasi pertama hingga terakhir yang masuk ke surga.
Berdasarkan ketiga keutamaan ini, hadits tersebut menurut As-Shan’ani tampaknya menegaskan bahwa mencintai bangsa Arab adalah suatu keharusan karena keistimewaan yang melekat pada mereka. Namun terdapat problem, di mana secara lahiriah, perintah ini bisa mencakup semua orang Arab, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. (At-Tanwir Syarhul Jami’ush Shagir, [Riyadh, Maktabah Darus Salam: 2011], jilid I, halaman 402). As-Shan’ani mengusung pandangan yang berseberangan dengan pemahaman populer masa kini. I
a menafsirkan bahwa hadits tentang kecintaan terhadap orang Arab mungkin merujuk khusus kepada orang yang beriman. Kemungkinan lainnya, jika meliputi semua orang Arab, maka kecintaan kepada non-Muslim Arab tertuju pada keindahan, kefasihan, dan kejernihan bahasa mereka, bukan keimanan, sementara kekufuran mereka tetap dibenci agama. Sebaliknya, jika hanya untuk orang Arab beriman, hadits ini menegaskan keunggulan mereka dalam kecintaan dibandingkan kaum beriman dari bangsa lain. (As-Shan’ani,I/402).
Pandangan As-Shan’ani di atas sulit diterima dalam konteks moral masyarakat modern, di mana kesetaraan dan penolakan terhadap rasisme telah menjadi pandangan yang mainstream. Kini, orang-orang meyakini bahwa perdamaian dapat dicapai melalui prinsip moral yang inklusif, bebas dari ujaran kebencian dan konflik yang dipicu oleh perbedaan. Mari kita simak penjelasan yang lebih inklusif dan cenderung moderat, yang berasal dari Mulla Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih.
Ia berpendapat, hadits bukanlah panggilan untuk chauvinisme etnis, atau sikap yang menyatakan bahwa satu ras, etnis dan bahasa lebih superior dibanding yang lainnya. Hanya saja, riwayat di atas dapat diposisikan sebagai penghargaan terhadap peran historis, linguistik, dan spiritual orang Arab dalam penyebaran Islam.
Penulis Mirqatul Mafatih menegaskan bahwa kecintaan ini berkaitan dengan “sebab dan faktor,” bukan sekadar identitas rasial. Riwayat ini juga mengundang refleksi tentang pentingnya memahami bahasa Arab untuk mendalami Al-Qur’an dan sunnah secara autentik. (Lama’atut Tanqih, [Beirut, Darul Fikr: 2002], jilid IX, halaman 3874).
Mungkinkah Penghuni Surga Berbahasa Bilingual? Pertanyaan tentang bahasa surga telah lama diperdebatkan dalam Islam. Pada abad ketujuh belas di Istanbul, isu ini muncul kembali saat gerakan puritan menentang penggunaan bahasa Persia dan kanon Persianate (tradisi budaya dan intelektual berbasis Persia) sebagai teks yang sakral. (Aslıhan Gürbüzel, Bilingual Heaven: Was There a Distinct Persianate Islam in the Early Modern Ottoman Empire?, [Philological encounters: 2021], halaman 214).
Para penulis Maulawiyah, tarekat sufi yang didirikan abad ke-13 di Konya oleh pengikut Rumi, membela kanon mistik Persianate dalam tradisi Islam Sunni pada abad ketujuh belas di Istanbul. Mereka mengusulkan konsep “surga bilingual,” dengan mensakralisasi bahasa Arab dan Persia. Menurut İsmāʿīl ʿAnḳaravī, seorang tokoh penting dalam tarekat Maulawiyah, Islam pada periode modern awal Ottoman tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga mengakui wacana non-hukum, seperti kanon mistik dan filosofis, sebagai bagian integral dari tradisi Islam.
Dalam imajeri surga bilingual, dua konfigurasi ilahi yang berbeda, yaitu hukum (legal) dan mistik-filosofis, dapat hidup berdampingan. Gagasan ini menunjukkan bahwa penghuni surga yang bilingual bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah kemungkinan yang dapat terjadi. (Gürbüzel, 217).
Ibnu Hazm Al-Andalusi berpendapat bahwa bahasa yang digunakan oleh penghuni surga dan neraka tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak ada teks atau konsensus (ijma') yang jelas mengenai hal ini. Ia menyatakan bahwa pasti ada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, yang bisa berupa salah satu bahasa yang dikenal manusia saat ini, bahasa baru yang berbeda dari semua bahasa yang ada, atau bahkan beberapa bahasa sekaligus (bilingual). (Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, [Beirut, Dar Ibni Hazm: 2016], jilid I, halaman 65). Lebih jauh, Ibnu Hazm menolak anggapan bahwa satu bahasa lebih unggul dari yang lain:
وقد توهم قوم في لغتهم أنها أفضل اللغات. وهذا لا معنى له لان وجوه الفضل معروفة، وإنما هي بعمل أو اختصاص ولا عمل للغة، ولا جاء نص في تفضيل لغة على لغة
Artinya, “Beberapa orang beranggapan bahwa bahasa mereka adalah yang terbaik. Namun, anggapan ini tidak memiliki makna karena keutamaan memiliki sebab yang jelas, yaitu melalui perbuatan atau keistimewaan tertentu. Bahasa itu sendiri tidak melakukan perbuatan, dan tidak ada teks yang menyatakan keunggulan satu bahasa atas yang lain.” (Al-Ihkam, jilid I, halaman 65).
Bahkan, Ibnu Hazm juga menolak klaim bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang terbaik atas bahasa lainnya hanya karena ia merupakan bahasa Qur’an. Ia menyebutkan: فأخبر تعالى أنه لم ينزل القرآن بلغة العرب إلا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك Artinya, “Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab semata-mata agar kaumnya (Nabi Muhammad saw) memahaminya, dan bukan karena alasan lain.” (Al-Ihkam, jilid I, halaman 66).
Selain itu, Ibnu Hazm juga mengutip pendapat Ali ra yang membantah orang-orang yang mengklaim bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik, “Pendapat ini tidak memiliki makna, karena Allah telah memberitahukan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya.” (Oday Zidat, The Origin of Human Language According to Ibn Ḥazm, [Al-Qasemi Journal of Islamic Studies: 2022], halaman 19).
Walhasil, perdebatan tentang bahasa di surga mencerminkan kompleksitas pandangan dalam Islam mengenai bahasa, identitas, dan otoritas keagamaan. Riwayat yang menyebutkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa surga telah dikritik dan dinilai lemah oleh banyak ulama ahli kritikus hadits.
Dengan demikian, bahasa Arab memang memiliki keistimewaan sebagai bahasa Al-Qur’an, tetapi tidak secara mutlak, dan tidak ada yang bisa memastikan menjadi bahasa tunggal di akhirat. Pandangan yang lebih moderat menekankan bahwa esensi Islam terletak pada keimanan dan amal, tanpa menafikan bahwa bahasa hanyalah sarana, bukan penentu nasib seseorang di akhirat. Wallahu a'lam.
(Ustadz Amien Nurhakim, Redaktur Keislaman NU Online dan Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta/nuonline, Sabtu, 15 Maret 2025)