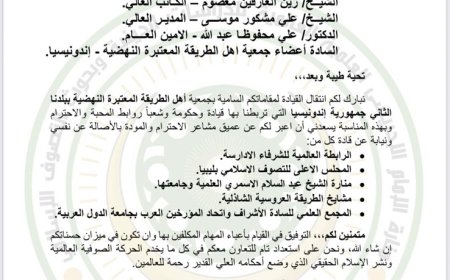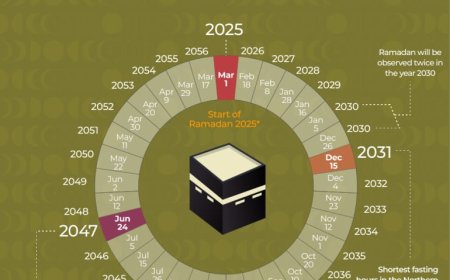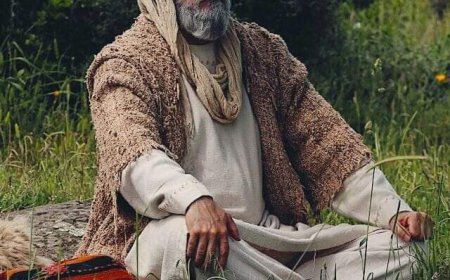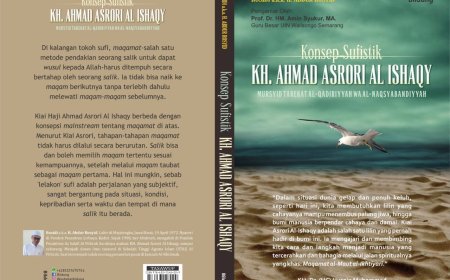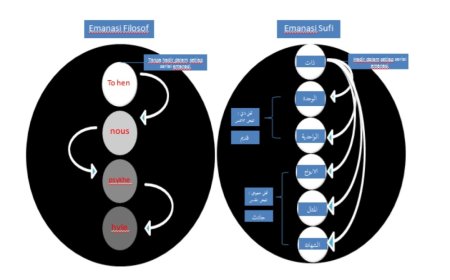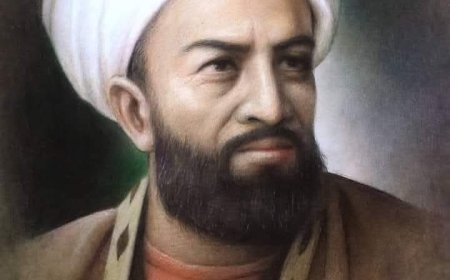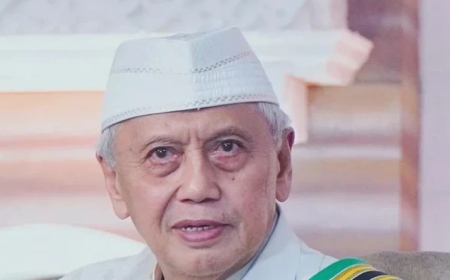Sastra Sebagai Jalan Diplomasi untuk Peroleh Pengakuan Kemerdekaan RI dari Dunia Internasional

Jakarta, JATMAN Online – Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Universitas Indonesia (UI), Prof. Muhammad Luthfi, M.A., Ph.D., mengatakan karya sastra dapat menjadi media diplomasi yang andal untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana yang dilakukan sastrawan di Palestina dan Indonesia.
Hal ini diungkapkan dalam orasi ilmiahnya pada Sabtu (10/12) lalu yang berjudul “Sastra sebagai Media Diplomasi dalam Upaya Memperoleh Pengakuan Kemerdekaan”, yang memaparkan peran penting politik sastra dalam diplomasi budaya.
Dikutip dari laman resmi ui.ac.id, Jumat (16/12), telah tercatat dalam sejarah bahwa setelah pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum mendapat pengakuan dari komunitas internasional.Salah satu jalan yang ditempuh untuk mendapat pengakuan tersebut adalah dengan jalur diplomasi, baik berupa government to government maupun people to people.
Dalam diplomasi government to government, Pemerintah Indonesia menggalang dukungan internasional dengan mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Haji Agus Salim untuk meyakinkan dunia internasional, khususnya negara-negara Arab, agar mengakui kemerdekaan Indonesia.
Sementara itu, dalam diplomasi people to people, Ali Ahmad Bakatsir–salah seorang sastrawan berkebangsaan Indonesia keturunan Hadramaut–berperan penting dalam meyakinkan masyarakat Arab atas kemerdekaan Indonesia. Diplomasi melalui media sastra yang dilakukan Bakatsir membuat Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang disusul oleh negara-negara Arab lainnya.
Salah satu drama Bakatsir yang berjudul “Audatul Firdaus” yang dipentaskan di Kairo Mesir, menjadi karya pemantik pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia. Drama yang terdiri atas empat babak ini menceritakan perdebatan tokoh-tokoh pendukung Sutan Syahrir dan Soekarno menjelang kemerdekaan Indonesia.
Dalam cerita tersebut, digambarkan bahwa upaya yang dilakukan Syahrir dan Soekarno dalam meraih kemerdekaan bukanlah perbedaan yang prinsipil, melainkan taktik yang berbeda untuk meraih tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia.
“Salah satu poin penting dalam cerita drama ini adalah nama Soekarno sebagai presiden RI pertama ditambahkan kata Ahmad sehingga disebut dengan Ir. Ahmad Soekarno. Nama Ahmad Sukarno-lah yang kemudian menjadi populer di Mesir. Oleh karena itu, rakyat Mesir mengetahui bahwa Indonesia yang baru saja merdeka adalah negara muslim yang dipimpin oleh seorang muslim, sehingga perlu didukung kemerdekaannya oleh bangsa Mesir,” ujar Prof. Luthfi.
Menurut Prof. Luthfi, penggunaan sastra sebagai media untuk mengekspresikan ide sosial dan politik merupakan sesuatu yang lazim di dunia sastra, termasuk sastra Arab. Kesusastraan Arab berperan dalam revolusi kebudayaan pada masa pendudukan Napoleon Bonaparte di Mesir (1798–1801). Napoleon datang ke Mesir tidak hanya membawa pasukan tentara, tetapi juga 167 ilmuwan dan mesin cetak, lalu mendirikan lembaga ilmiah dengan nama Institute d’Egypte yang terbagi dalam beberapa bidang, termasuk ilmu sastra dan seni.
Dikerahui, bahwa lembaga tersebut mengelola penerbitan Le Decade Egyptienne yang menerbitkan majalah, surat kabar, dan buku termasuk karya sastra. Buku-buku yang diterbitkan tersebut selain membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, juga memperkenalkan ideologi baru yang berasal dari ide revolusi Perancis, yaitu liberty, equality, and fraternity (kebebasan, keadilan, dan persaudaraan). Ideologi baru tersebut menjadi pendorong kebangkitan kesusastraan Arab modern yang akhirnya memicu lahirnya revolusi kebudayaan di Mesir dan dunia Arab pada umumnya.
Sastrawan Arab seperti Mahmoud Darwish, Nizar Qabbani, dan Fadwa Tuqan merupakan kalangan yang menjadikan karyanya sebagai media untuk memperjuangkan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Darwish menyampaikan ide perjuangan kemerdekaan Palestina melalui puisi, begitu pula Fadwa yang merupakan penyair wanita Palestina yang melahirkan puisi diplomasinya setelah peristiwa Nakba (penderitaan) dalam Perang Enam Hari pada 1967. Sementara itu, Qabbani merupakan diplomat Suriah yang berdinas sebagai Atase Kebudayaan di berbagai negara, namun akhirnya mengundurkan diri pada 1966 untuk menekuni dunia sastra.