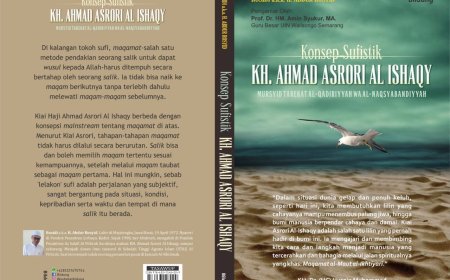Mengenal Kiai Noer Iskandar; Sosok Kiai Desa Penakluk Ibu Kota
Ditulis oleh: Muhammad Fathul Bari, Mahasantri Ma’had Aly Sa’iidusshiddiqiyah Jakarta. Alumnus Pesantren TQ Roudlotut Tholibin Purworejo

Kota dan desa merupakan dua dimensi yang jauh berbeda bahkan saling bertolak belakang. Perbedaan tersebut tercermin dalam banyak hal seperti kultur, budaya, adat, dan adab. Budaya kota biasanya tidak cocok dibawa ke desa begitupun sebaliknya, budaya desa akan dianggap ’kampungan’ jika dibawa ke kota. Namun, bukan berarti keduanya mustahil bersatu. Fakta di lapangan menunjukkan banyak kiai yang sukses melawan stigma itu, di antaranya adalah KH. Noer Muhammad Iskandar Banyuwangi.
Kiai Noer, sapaan akrabnya, merupakan putra ke sembilan dari pasangan Kiai Askandar dan Nyai Siti Robiatun. Ayahnya, Kiai Askandar merupakan ulama terpandang asal Banyuwangi dengan jumlah santrinya yang mencapai ribuan. Sebagai putra kiai kondang, Kiai Noer tentu digadang-gadang akan menjadi pengganti ayahnya dalam memimpin pesantren kelak. Namun, kiai kelahiran Banyuwangi, 5 Juli 1955 ini adalah sosok pejuang pesantren yang berbeda dari kebanyakan kiai pada umumnya.
Alih-alih meneruskan pesantren ayahnya, Kiai Noer memilih untuk merintis pesantrennya sendiri di tengah jantung Ibu Kota Jakarta. Tentu hal itu bukan hal yang mudah. Secara kultur, Kiai Noer mempunyai latar belakang pedesaan yang kental. Ia mengenyam pendidikan di pesantren tradisional yang kental akan nuansa desa pula, seperti Lirboyo. Namun, mendirikan pesantren di Jakarta bukan semata-mata keinginan pribadi Kiai Noer, melainkan berangkat dari titah sang guru, KH Mahrus Aly Lirboyo.
Pendidikan Kiai Noer
Nampaknya kecerdasan Kiai Noer berkat didikan sang ayah, Kiai Askandar. Kiai Noer belajar ilmu agama dasar di pesantren ayahnya sendiri, Manbaul Ulum Sumber Beras, Muncar, Banyuwangi. Meskipun Ia putra pemilik pesantren itu sendiri, namun Kiai Askandar tidak memperlakukan putranya itu dengan perlakuan layaknya putra kiai. Kiai Askandar bahkan cenderung bersikap keras terhadap Kiai Noer. Contohnya seperti larangan Kiai Askandar dalam memakai gelar ‘gus’ yang dinisbatkan kepada putranya itu.
Setelah menamatkan pendidikan dasarnya di Manbaul Ulum, pada tahun 1967, Kiai Noer berangkat nyantri ke Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur dibawah asuhan langsung KH Mahrus Aly selama enam tahun. Selama di Lirboyo inilah Kiai Noer menonjolkan kecerdasannya. Ia dipercaya menjadi rais musyawarah di pesantren. Disaat itu pula bakat menjadi da’i Kiai Noer mulai terbentuk.
Setelah tamat dari Lirboyo, pada tahun 1974, Kiai Noer memilih menyeberang kedalam dunia akademik dengan berkuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Tentu hal itu atas rekomendasi dari pimpinan pesantren Lirboyo.
Dengan begitu, selain sebagai bentuk ‘nderek dawuh’ terhadap gurunya, juga atas dasar keinginan Kiai Noer sendiri yang ingin memperdalam ilmu Al-Qur’an secara akademis. Pada saat kuliah di PTIQ lah bakat da’i Kiai Noer semakin terasah. Ia mulai biasa mengisi ceramah-cermaah agama baik di internal kampus maupun luar kampus.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di PTIQ pada tahun 1982, Tak berselang lama sarjana muda ini melepas masa lajangnya di berusia 27 tahun dengan menikahi putri Kiai Mashudi asal Tumpang, Malang, Jawa Timur bernama Siti Nur Djazilah.
Isyarat Sang Guru
Di antara kisah menarik dari awal mula perjuangan Kiai Noer adalah pesan yang disampaikan KH mahrus Aly. Dalam khutbah pernikahan Kiai Noer, Mbah Mahrus Aly berpesan setelah menikah nanti agar dirinya tidak kembali ke Banyuwangi ataupun Malang ke kediaman sang istri, begitu juga tidak diperkenankan mengabdi di Lirboyo, melainkan diminta agar tetap berdakwah di Jakarta. Hal itu seakan menjadi isyarat kelak Kiai Noer akan menjadi tokoh berpengaruh di Ibukota. Sebagai seorang santri, Kiai Noer tentu mengiyakan pesan kiainya tersebut.
Seminggu setelah pernikahan, Kiai Noer dan sang istri berangkat ke Jakarta menunaikan pesan sang guru. Karen belum punya tempat tinggal, Kiai Noer menumpang hidup kepada teman-temannya. Hal itu terus dilakukan dengan berpindah dari rumah satu ke rumah yang lain dengan maksud ingin memperkenalkan istrinya kepada teman-temannya. Pada akhirnya Kiai Noer menitipkan istrinya kepada keponakannya, Drs. Marsidah Tahir di Ciputat.
Kehidupan di Jakarta
Sembari mencari sumber penghidupan, Kiai Noer mulai memantapkan kembali lembaga pendidikan yang pernah ia dirikan bersama teman kuliahnya sewaktu masih menjadi mahasiswa PTIQ, yaitu Yayasan Al-Muchlisin di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan keagamaan mulai digiatkan, kegiatan remaja masjid mulai dikembangkan. Seiring berjalannya waktu, segala aktivitas yang dijalankan Kiai Noer mulai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga permintaan undangan ceramah mulai berdatangan.
Tiga bulan kemudian, Kiai Noer mulai memberanikan diri untuk ngontrak di Bilangan Kebon Jeruk. Kiai Noer merasa tidak enak kepada keponakannya jika berlama-lama membiarkan istrinya menumpang. Setelah itu, Kiai Noer tetap menjalankan aktivitasnya sebagai pendakwah. Kepercayaan masyarakat kian meningkat. Kegiatan semakin padat, undangan ceramah semakin membludak bahkan hingga luar Jakarta. Kiai Noer juga dipercaya untuk mengisi ceramah rutin mingguan di salah satu stasiun radio.
Lama-kelamaan, nama Kiai Noer Iskandar semakin populer di benak masyarakat. Ia bahkan dijuluki tiga serangkai saat itu, yaitu Kiai Noer Iskandar, Kiai Zainuddin MZ dan Raja Dangdut Rhoma Irama. Karier Kiai Noer kian melesat dalam mewarnai panggung da’i nasional. Ceramahnya banyak diliput baik di TV maupun stasiun radio. Kiai Noer juga pernah mendapat durian runtuh karena dapat menunaikan ibadah Haji berkat jasa sahabatnya, Ir. H. Bambang Sudaryanto.
Tentu hal itu bukan tanpa sebab. H Bambang yang merupakan kepala PPL Pluit pernah meminta doa kepada Kiai Noer terkait pekerjaanya. Setelah sukses, H Bambang memberikan hadiah sebagai ucapan terimakasih kepada Kiai Noer berupa kios kecil di Pluit ditambah biaya berangkat Haji. Namun sayang, pendaftaran haji waktu itu sudah ditutup.
Tidak mau menunda keberangkatan, Kiai Noer kemudian menemui kawan lamanya, H Rosyidi Ambari yang telah menjadi asisten Menteri Agama saat itu. Keajaiban pun terjadi lagi, saat menemuinya, ternyata kawannya ini terlah lama mencari keberadaan Kiai Noer untuk diminta mengelola sebidang tanah wakaf di Kedoya untuk dijadikan Lembaga Pendidikan.
Mendirikan Asshiddiqiyah
Tawaran tanah wakaf itu tidak serta merta diterima begitu saja oleh Kiai Noer. Ia perlu mendapat ‘isyarat langit’ untuk mengiyakannya. Apalagi disitu sudah ada pondasi pesantren dan plang pesantren bertuliskan Ukhwah Islamiyah disitu. Tentu ini merupakan amanah dan tanggungjawab besar. Saat itu, Kiai Noer baru mempunyai satu anak, yaitu Noor Eka Fatimatuzzahra.
Sepulangnya dari tanah suci, atas kesepakatan sang istri dan juga konsultasi ke beberapa kiai, Kiai Noer mantap untuk menerima tawaran itu. Setelah menemui H Rosyidi Ambari, Ia diajak menemui sang wakif, yaitu H Djaani di Kedoya. Akhirnya, lahan wakaf itu yang tadinya dipercayakan kepada H Rosyidi dialihkan kepada Kiai Noer. Kiai Noer mengubah nama dari Ukhwah Islamiyah menjadi Ashiddiqiyah.
Langkah pertama yang diambil Kiai Noer adalah membangun mushala kecil dengan modal dari H Abdul Ghani, putra ketiga H Djaani. Mushola itu terbuat dari triplek dan berdiri di tanah rawa-rawa. bahkan dulunya adalah tempat pembuangan sampah bagi warga perumahan disekitar situ.
Sebelum berangkat haji, Kiai Noer sempat berpikir untuk menyerah dan kembali ke Banyuwangi atau Cukir karena terkendala ekonomi. Namun, niat itu diurungkan setelah melihat bangunan yang akan menjadi Pondok Pesantren Asshiddiqiyah. Kiai Noer sadar bahwa di lahan itu perlu didirikan sebuah yayasan. Oleh karena itu, bersama H Abdul Ghani dan H Rosyidi Ambari, Kiai Noer langsung menghadap notaris.
Pada 5 Oktober 1985, Kiai Noer bersama H Abdul Ghani dan H Rosyidi Ambari ditetapkan sebagai Badan Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Asshiddiqiyah. Belakangan, ketiga tokoh tersebut dikenal sebagai Trimurti Asshiddiqiyah.
Santri Generasi Pertama
Saat Asshiddiqiyah membuka pendaftaran santri, sambutan masyarakat belum ada. Bahkan pada tahun pertama, Kiai Noer hanya menerima satu santri. Itu pun calon santri Pesantren Manba'ul Ulum asuhan sang ayah. Kebetulan nama santri itu adalah Iskandar yang berasal dari Lampung. Selang tujuh bulan Iskandar menuntut ilmu di sana, datanglah seorang santri Perempuan dari Kuningan Jawa Barat bernama Rohanah. Merekalah santri generasi pertama Pondok Pesantren Asshiddiqiyah.
Asshiddiqiyah membuka sistem pendidikannya dengan metode Ribathiyah, yaitu sistem belajar menggunakan halaqah tradisional ala pesantren desa. Para santri belajar dan mengaji kepada guru atau kiai sambil memegang satu bidang pekerjaan di pondok. Kiai Noer juga mengajar ‘santri kalong’ yang bermukim disekitaran pesantren. Berbekal kegiatan mengajarnya itu, Kiai Noer kemudian mendirikan madrasah formal pada 1986.
Asshiddiqiyah Mulai Berkembang
Pada 1986, Madrasah Tsanawiyah dibuka. Murid pertamanya tentu santri Ribathiyah. Karena di kota besar, Kiai Noer tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan guru-guru muda yang punya semangat juang dan cita-cita tinggi. Beliau juga melibatkan para sarjana dan alumni pesantren salaf untuk mengajar santri-santrinya.
Setahun berjalan, Madrasah Tsanawiyah mulai berhasil memikat hati masyarakat. Terbukti, pada tahun kedua Kiai Noer sudah harus membuka madrasah aliyah. Kiai Noer percaya bahwa peningkatan tersebut merupakan sebuah amanat yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga.
Tahun demi tahun berlalu. Kepercayaan masyarakat pun semakin meningkat. Ketika santri di Kedoya tidak bisa ditampung lagi, Kiai Noer menerima tanah wakaf dari H. Jauhari dan H. Musa di Batu Ceper, Tangerang, Banten. Lahan seluas satu hektar diserahkan untuk dikembangkan Asshiddiqiyah. Selain itu, Kiai Noer juga diberi kepercayaan untuk mengelola tanah H. Sayuthi di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat menyusul di Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat.
Dalam waktu singkat, Asshidiqiyah bertransformasi dari yang tadinya hanya memilik beberapa santri menjadi pesantren raksasa dengan total puluhan ribu santri. Bahkan kini alumninya juga menyebar di segala bidang profesi, mulai dari petani, peternak, pedagang, pengusaha, pejabat, politikus, bahkan hingga duta besar. Itulah yang selalu diwanti-wanti oleh Kiai Noer agar santrinya tidak harus menjadi pendakwah, tetapi bisa menjadi apapun sesuai bakat dan potensi santri itu sendiri.
Kini, Asshiddiqiyah telah berkembang menjadi dua belas cabang yang tersebar di Jawa dan Sumatra, antara lain Asshiddiqiyah Pusat Jakarta Barat; Asshiddiqiyah 2 Batuceper Tangerang; Asshiddiqiyah 3, 4, 5, Karawang; Asshiddiqiyah 6 Serpong Tangerang Selatan; Asshiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor; Asshiddiqiyah 8 Musi Banyuasin; Asshiddiqiyah 9 Gunungsugih Lampung Tengah; Asshiddiqiyah 10 Cianjur; Asshiddiqiyah 11 Way Kanan; dan Asshiddiqiyah Jonggol.
*) Tulisan ini disarikan dari buku Pergulatan membangun Pesantren karya Amin Idris (2009).